Sekolah Negeri: Pabrik Generasi Produktif atau Formalitas?
Setiap tahun, jutaan siswa mengenakan seragam putih-abu dan putih-biru. Mereka berbondong-bondong memasuki gerbang sekolah negeri dari Sabang hingga Merauke. Mereka membawa harapan menjadi generasi emas yang akan mengerek kemajuan bangsa. Namun, di balik seragam rapi dan buku pelajaran yang tebal, sebuah pertanyaan menggelayut. Apakah sekolah negeri dari SD hingga SMA benar-benar mampu mencetak generasi yang produktif? Apakah mereka siap bersaing di era disrupsi teknologi dan globalisasi?
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024 mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka lulusan SMA mencapai 7,86%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan lulusan perguruan tinggi yang hanya 5,63%.
Angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah cerminan paradoks. Sekolah negeri menjadi tumpuan pendidikan massal di Indonesia. Sekolah-sekolah ini tampaknya gagal mengantarkan lulusannya ke dunia kerja. Dunia kerja menuntut keterampilan nyata, bukan sekadar nilai di rapor.
Sekolah negeri sangat banyak, dengan lebih dari 200,000 unit dari SD hingga SMA. Anggaran pendidikan nasional sebesar 20% APBN. Sekolah ini diharapkan menjadi mesin pembentuk sumber daya manusia unggul.
Sejak reformasi pendidikan digulirkan mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi hingga Kurikulum Merdeka. Pemerintah berjanji untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya pandai menghafal. Pemerintah juga berjanji untuk melahirkan individu yang kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Namun, realitas di lapangan berkata lain.
Banyak lulusan sekolah negeri merasa tersesat ketika memasuki dunia kerja. Mereka kekurangan keterampilan praktis seperti literasi digital, kemampuan berpikir kritis, atau bahkan dasar-dasar kewirausahaan.
Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan bahwa siswa Indonesia masih tertinggal jauh dalam literasi. Dalam matematika dan sains, mereka juga tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia.
Skor rata-rata literasi Indonesia hanya 359, jauh di bawah rata-rata OECD sebesar 474. Apakah ini pertanda bahwa sistem pendidikan negeri kita lebih sibuk mengejar angka-angka di kertas ketimbang membentuk generasi yang benar-benar produktif?
Di tengah sorotan publik terhadap kualitas pendidikan, sekolah negeri sering dipuji sebagai simbol kesetaraan. Mereka menawarkan pendidikan terjangkau bagi jutaan anak bangsa. Namun, kesetaraan itu kerap hanya ilusi.
Ketimpangan fasilitas antara sekolah di perkotaan dan pedesaan adalah masalah. Kualitas guru yang bervariasi juga menyebabkan kendala. Selain itu, kurikulum yang masih terpaku pada ujian standar menjadi batu sandungan. Dunia kerja menuntut kemampuan beradaptasi dan inovasi. Namun, banyak siswa sekolah negeri masih disibukkan dengan hafalan rumus. Teori yang mereka pelajari jauh dari kebutuhan praktis.
Industri pun mengeluh: lulusan SMA negeri kerap kali tidak memiliki soft skills seperti komunikasi atau kerja tim. Apalagi, mereka seringkali kekurangan hard skills seperti penguasaan teknologi. Lantas, jika sekolah negeri adalah fondasi pendidikan nasional, mengapa fondasi ini tampak rapuh? Apakah sistem ini memang dirancang untuk mencetak generasi produktif, atau hanya melanggengkan lini produksi nilai yang terputus dari realitas? Pertanyaan ini bukan sekadar kritik, melainkan panggilan untuk meninjau ulang visi pendidikan kita.
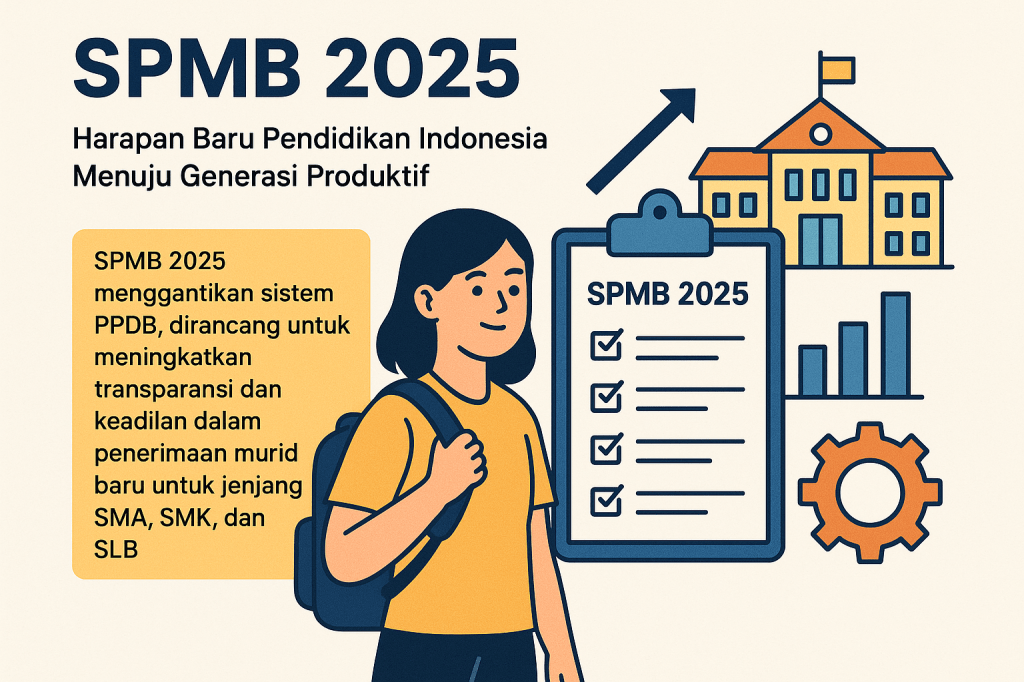
Kelemahan Sistem Pendidikan Negeri
Di balik cita-cita luhur sekolah negeri sebagai pilar pendidikan nasional, ada realitas di lapangan yang menyingkap luka sistemik. Hambatan ini menghalangi lahirnya generasi produktif. Kurikulum, yang seharusnya menjadi jantung pendidikan, sering kali terjebak dalam kerangka kaku yang mengutamakan hafalan ketimbang keterampilan praktis. Meski Kurikulum Merdeka diperkenalkan pada 2022 untuk mendorong pembelajaran berbasis proyek dan fleksibilitas, implementasinya masih timpang.
Berdasarkan laporan Kemendikbudristek 2024, hanya 34% sekolah negeri di daerah terpencil mampu menerapkan kurikulum ini secara penuh. Hal ini terjadi karena keterbatasan sumber daya. Siswa SD hingga SMA masih disuguhi pelajaran yang berfokus pada ujian nasional atau asesmen standar. Mereka tidak mempelajari keterampilan abad 21 seperti literasi digital, pemecahan masalah, atau kewirausahaan. Akibatnya, lulusan sekolah negeri kerap kali tidak siap menghadapi dunia kerja yang menuntut inovasi dan adaptasi. Apakah pendidikan kita benar-benar dirancang untuk mencetak generasi produktif, atau hanya melatih siswa untuk lulus ujian?
Kualitas guru, sebagai ujung tombak pendidikan, juga menjadi titik lemah. Data dari Program Guru Penggerak menunjukkan sebuah kenyataan. Hanya 15% guru di sekolah negeri pada 2024 akan memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi modern. Banyak guru masih menggunakan metode mengajar konvensional. Metode ini termasuk ceramah satu arah. Hal ini terjadi karena minimnya pelatihan profesional. Beban administratif yang menyita waktu juga menjadi faktor.
Di beberapa daerah, guru honorer bergaji di bawah Rp1 juta per bulan. Mereka harus mengajar hingga 40 siswa per kelas. Tidak ada akses ke teknologi pendukung. Bagaimana mungkin pendidikan berkualitas lahir dari kondisi seperti ini? Ketimpangan ini diperparah oleh disparitas fasilitas. Sekolah negeri di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya sering kali dilengkapi laboratorium komputer dan akses internet. Sementara itu, sekolah di pedalaman Nusa Tenggara Timur atau Papua masih berjuang dengan papan tulis dan buku pelajaran usang. Laporan Bank Dunia 2023 mencatat bahwa 60% sekolah negeri di daerah tertinggal tidak memiliki fasilitas laboratorium sains. Ini merupakan kebutuhan dasar untuk membangun keterampilan analitis.
Hasilnya terlihat jelas pada capaian siswa. Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menempatkan Indonesia di peringkat 71 dari 79 negara dalam literasi, matematika, dan sains. Skor rata-rata Indonesia adalah 359, yang jauh di bawah rata-rata global.
Ini bukan sekadar angka. Ini adalah cerminan bahwa sistem pendidikan negeri kita gagal. Sistem ini tidak membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis. Ini juga tidak melatih mereka menyelesaikan masalah nyata. Dunia industri pun merasakan dampaknya.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam laporan 2024 menyatakan bahwa 65% lulusan SMA negeri tidak memenuhi standar keterampilan dasar. Keterampilan dasar tersebut meliputi komunikasi efektif. Selain itu, penguasaan teknologi dasar juga termasuk di dalamnya. Sistem pendidikan negeri, yang seharusnya menjadi fondasi bangsa, tampak lebih sibuk mengejar target kelulusan ketimbang mempersiapkan siswa untuk dunia nyata.
Pertanyaan pun mengemuka: jika sekolah negeri hanya melahirkan lulusan yang pandai menghafal tetapi miskin keterampilan, bagaimana mereka akan bersaing? Mampukah mereka bertahan di era yang menuntut produktivitas tinggi?
Menuju Penurunan Angka Pengangguran
Jika dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, Sekolah Negri dapati menjadi alat strategis dalam menurunkan angka pengangguran nasional. Dengan:
- Penempatan siswa yang tepat pada jalur pendidikan (SMA/SMK/SLB),
- Pendidikan vokasional yang selaras dengan kebutuhan industri, dan
- Akses pendidikan yang lebih merata secara sosial dan geografis,
maka akan terbentuk generasi muda yang siap kerja, mandiri, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
“Pendidikan bukan hanya tentang siapa yang bisa sekolah. Ini tentang bagaimana negara memastikan setiap anak tumbuh dengan kesempatan yang sama untuk sukses.”




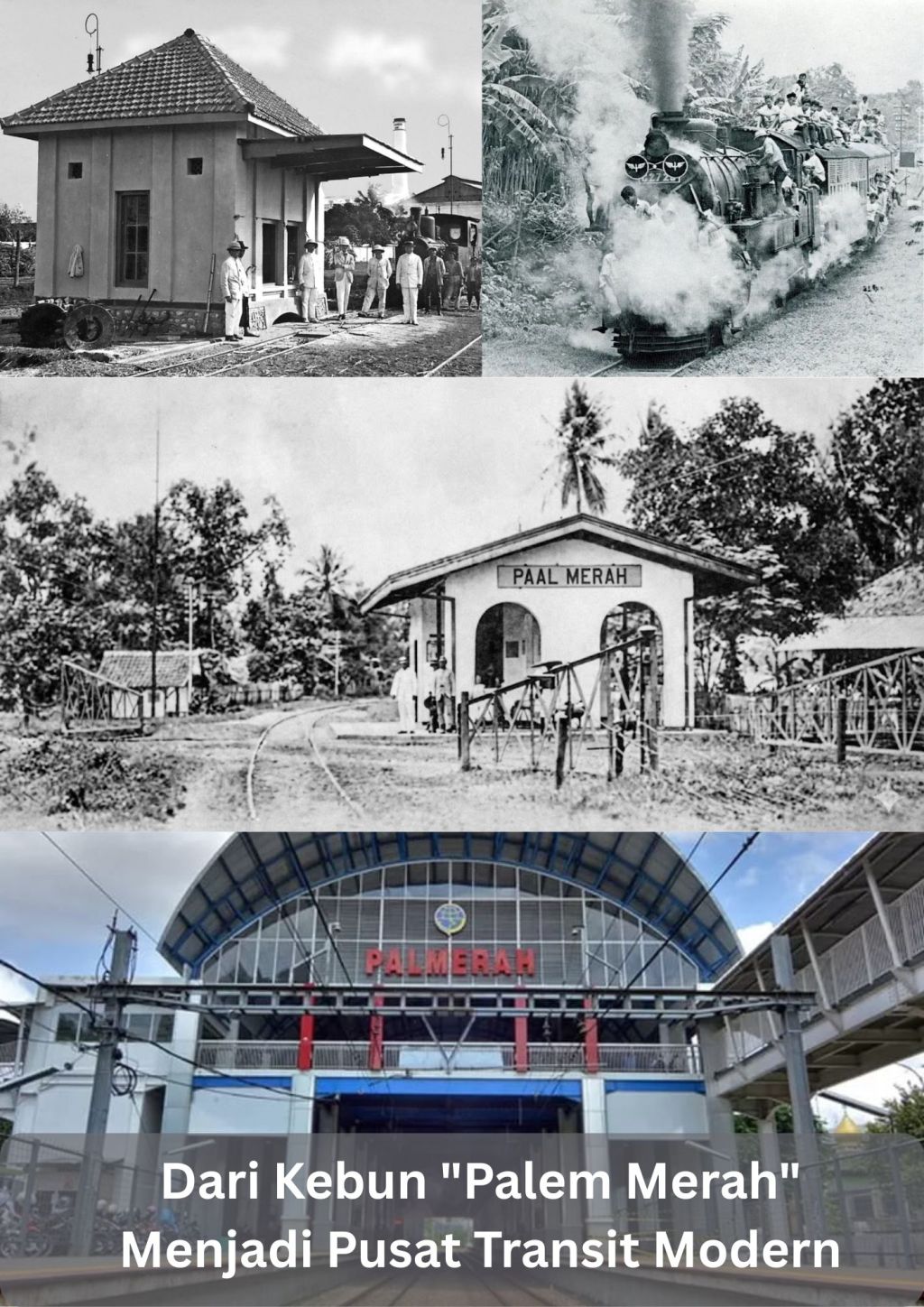
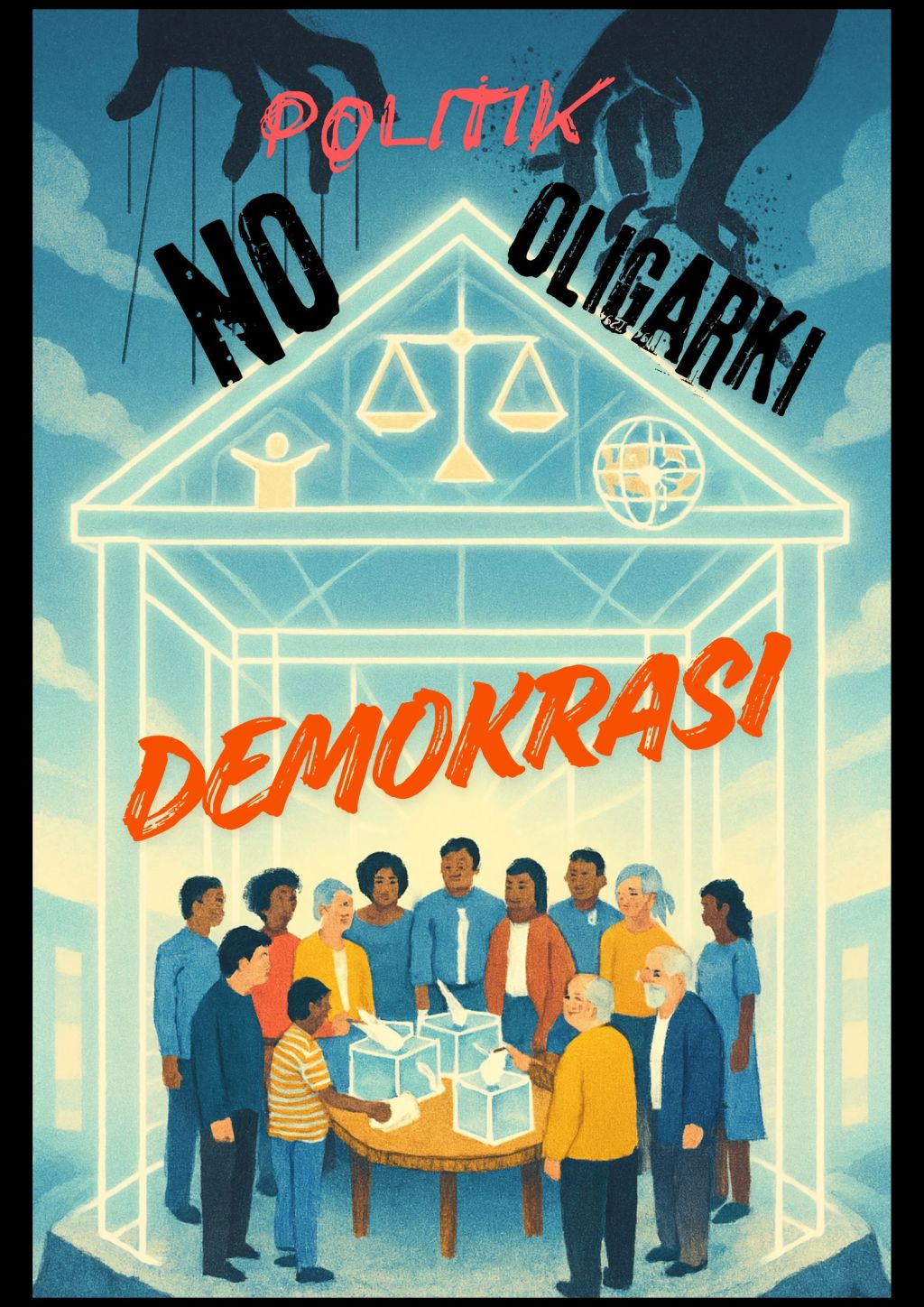




Leave a comment