Korupsi di Indonesia terus menjadi momok yang menggerogoti fondasi demokrasi. Anggota partai politik (parpol) di legislatif dan eksekutif kerap menjadi pelaku utama.
Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat serangkaian skandal korupsi. Skandal ini melibatkan anggota DPR dan pejabat parpol. Tuduhan bahwa parpol di Indonesia dibentuk dengan niat terselubung untuk korupsi pun muncul.
Indikator kuat adalah kegagalan DPR dan parpol. Mereka tidak mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset bagi koruptor. Kebijakan ini dianggap kunci untuk memutus rantai korupsi sistemik.
Ketua-ketua umum parpol diharapkan menjadi motor reformasi. Namun, mereka justru dinilai tidak memiliki political will untuk meniru langkah tegas. Langkah tegas ini diambil oleh negara seperti Tiongkok dan Singapura dalam menciptakan Indonesia bebas koruptor.
Korupsi sebagai DNA Parpol?
Tuduhan bahwa parpol di Indonesia dibentuk dengan niat korupsi bukanlah hal baru. Namun, hal ini semakin mengemuka seiring terkuaknya kasus-kasus besar di 2025.
Dua anggota DPR periode 2019-2024, Heri Gunawan dari Partai Gerindra dan Satori dari Partai NasDem, menjadi sorotan. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dana yang seharusnya untuk masyarakat itu diduga mengalir ke kantong pribadi. Aliran dana bahkan sampai ke kas partai. Hal ini menambah daftar panjang skandal korupsi yang melibatkan elite parpol.
Namun, kasus ini hanyalah puncak gunung es. Laporan KPK menunjukkan bahwa dari 2019 hingga 2025, lebih dari 30 anggota DPR dari berbagai parpol terjerat kasus korupsi. Kasus-kasus tersebut termasuk suap proyek infrastruktur, penyalahgunaan dana bansos, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Korupsi bukan lagi penyakit individual, tetapi sistemik. Parpol seolah menjadi kendaraan untuk mengamankan kepentingan pribadi dan kelompok.
Tuduhan bahwa parpol dibentuk dengan niat korupsi diperkuat oleh sikap DPR yang terus menunda pembahasan RUU Perampasan Aset.
UU ini, yang telah diusulkan sejak 2012, dianggap sebagai terobosan. Ini memungkinkan penyitaan aset hasil korupsi tanpa proses pidana yang panjang. Metode ini diterapkan di Tiongkok dan Singapura.
Namun, hingga akhir 2025, RUU ini masih terkatung-katung di DPR, dengan alasan “kurangnya konsensus” antar-fraksi. “Ini bukan soal teknis, tapi soal niat. Parpol di DPR tahu. UU ini akan mengancam kepentingan mereka sendiri,” kata aktivis anti-korupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana.
Kegagalan Political Will Ketua Umum Parpol
Ketua umum parpol, sebagai figur sentral dalam menentukan arah kebijakan, dinilai gagal menunjukkan komitmen melawan korupsi. Dari sembilan parpol yang memiliki kursi di DPR periode 2024-2029, tidak ada ketua umum yang secara terbuka mendorong reformasi anti-korupsi. Tidak ada yang mengupayakan reformasi secara radikal. Sebaliknya, banyak di antara mereka yang justru terlibat dalam kontroversi atau melindungi kader yang tersangkut kasus hukum.
Sebagai contoh, meskipun Partai Gerindra dan NasDem mengklaim memiliki kode etik internal, kasus Heri Gunawan menunjukkan lemahnya pengawasan partai. Kasus Satori juga menunjukkan hal yang sama. “Jika ketua umum serius, mereka akan mendukung penonaktifan anggota yang jadi tersangka dan mendorong audit transparan atas dana partai. Tapi yang kita lihat justru pembelaan atau pembiaran,” ujar Kurnia.
Bandingkan dengan Tiongkok. Partai Komunis menerapkan kebijakan “harimau dan lalat” untuk menindak koruptor. Mereka menarget dari pejabat tinggi hingga rendah. Hukuman yang dijatuhkan sangat berat hingga eksekusi.
Singapura juga dikenal dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) yang independen dan efektif. Dukungan UU memungkinkan perampasan aset tanpa pandang bulu. “Di Indonesia, parpol seolah alergi dengan model ini. Mereka lebih suka mempertahankan status quo,” tambah Andi Widjajanto.
Pola Korupsi Sistemik di Parpol
Korupsi yang melibatkan anggota parpol tidak terbatas pada legislatif. Di tingkat eksekutif, pejabat parpol yang menjabat sebagai menteri atau gubernur juga kerap terseret skandal. Gubernur Riau Abdul Wahid dari PKB, misalnya, menjadi sorotan. Ia terlibat dalam operasi tangkap tangan KPK pada 2025. Kasus tersebut terkait suap proyek pembangunan daerah. Kasus ini menggambarkan bagaimana parpol menjadi “mesin” untuk mengamankan akses ke sumber daya publik.
Pola ini diperparah oleh pendanaan parpol yang tidak transparan. Banyak pihak menduga bahwa dana kampanye parpol berasal dari sumber ilegal, termasuk gratifikasi dan suap. “Parpol butuh dana besar untuk pemilu. Ketika dana itu tidak jelas asalnya, korupsi menjadi solusi cepat,” ungkap Transparency International Indonesia dalam laporan terbarunya.
Sementara itu, kegagalan DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset memperlihatkan konflik kepentingan yang nyata. UU ini akan memungkinkan KPK menyita aset koruptor tanpa menunggu putusan pengadilan, sehingga mempersulit pelaku menyembunyikan hasil kejahatan. Namun, fraksi-fraksi di DPR masih menghambat. Mereka didominasi parpol besar seperti PDIP, Golkar, Gerindra, dan NasDem. Mereka terus berdalih perlunya “studi mendalam”. “Ini alasan klasik untuk melindungi kepentingan elite,” tegas Kurnia.
Dampak pada Kepercayaan Publik
Skandal demi skandal yang melibatkan parpol telah membuat kepercayaan publik terhadap demokrasi merosot. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Oktober 2025 menunjukkan bahwa hanya 23% masyarakat yang percaya DPR bekerja untuk kepentingan rakyat. Angka ini turun drastis dari 45% pada 2019. Media sosial juga dipenuhi kritik, dengan tagar seperti #ParpolKorup dan #ReformasiDPR menjadi trending di platform X.
Masyarakat sipil mendesak penonaktifan anggota DPR yang jadi tersangka. Termasuk di dalamnya ICW dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Mereka juga mendesak reformasi sistem pendanaan parpol. Namun, respons parpol cenderung defensif. Beberapa ketua umum bahkan menyebut kasus korupsi sebagai “serangan politik” terhadap partai mereka, alih-alih mengakui kelemahan internal.
Meniru Tiongkok dan Singapura: Mungkinkah?
Tiongkok dan Singapura sering dijadikan contoh sukses dalam pemberantasan korupsi. Tiongkok menerapkan hukuman mati bagi koruptor kelas kakap. Singapura memiliki sistem pengawasan ketat. Mereka juga menawarkan gaji tinggi untuk pejabat publik guna mencegah suap. Namun, kedua model ini sulit diterapkan di Indonesia karena perbedaan sistem politik dan budaya hukum.
Meski begitu, langkah seperti pengesahan RUU Perampasan Aset bisa menjadi titik awal. UU ini akan memberikan efek jera dengan memiskinkan koruptor, sekaligus menutup celah pencucian uang melalui aset seperti properti atau saham. Sayangnya, tanpa political will dari ketua umum parpol dan DPR, UU ini berisiko tetap jadi wacana.
Langkah ke Depan
Untuk mengatasi krisis ini, beberapa langkah mendesak diperlukan:
- Pengesahan RUU Perampasan Aset: DPR harus segera memprioritaskan UU ini dengan tenggat waktu jelas, misalnya pertengahan 2026.
- Reformasi Pendanaan Parpol: Wajibkan transparansi sumber dana kampanye dan audit independen oleh KPK.
- Sanksi Tegas: Parpol harus pecat kader yang jadi tersangka dan mendukung penegakan hukum.
- Edukasi Publik: Dorong kesadaran masyarakat melalui kampanye anti-korupsi di media sosial dan pendidikan sipil.
Kesimpulan
Tuduhan bahwa parpol di Indonesia dibentuk dengan niat korupsi mungkin terdengar provokatif. Namun, ini sulit dibantah ketika DPR dan ketua umum parpol terus menunjukkan keengganan untuk reformasi. Kegagalan mengesahkan RUU Perampasan Aset dan lemahnya pengawasan internal parpol menjadi bukti kurangnya political will untuk menciptakan Indonesia bebas koruptor. Jika Tiongkok dan Singapura bisa, mengapa Indonesia tidak? Pertanyaan ini harus dijawab oleh elite parpol, sebelum kepercayaan publik benar-benar habis.





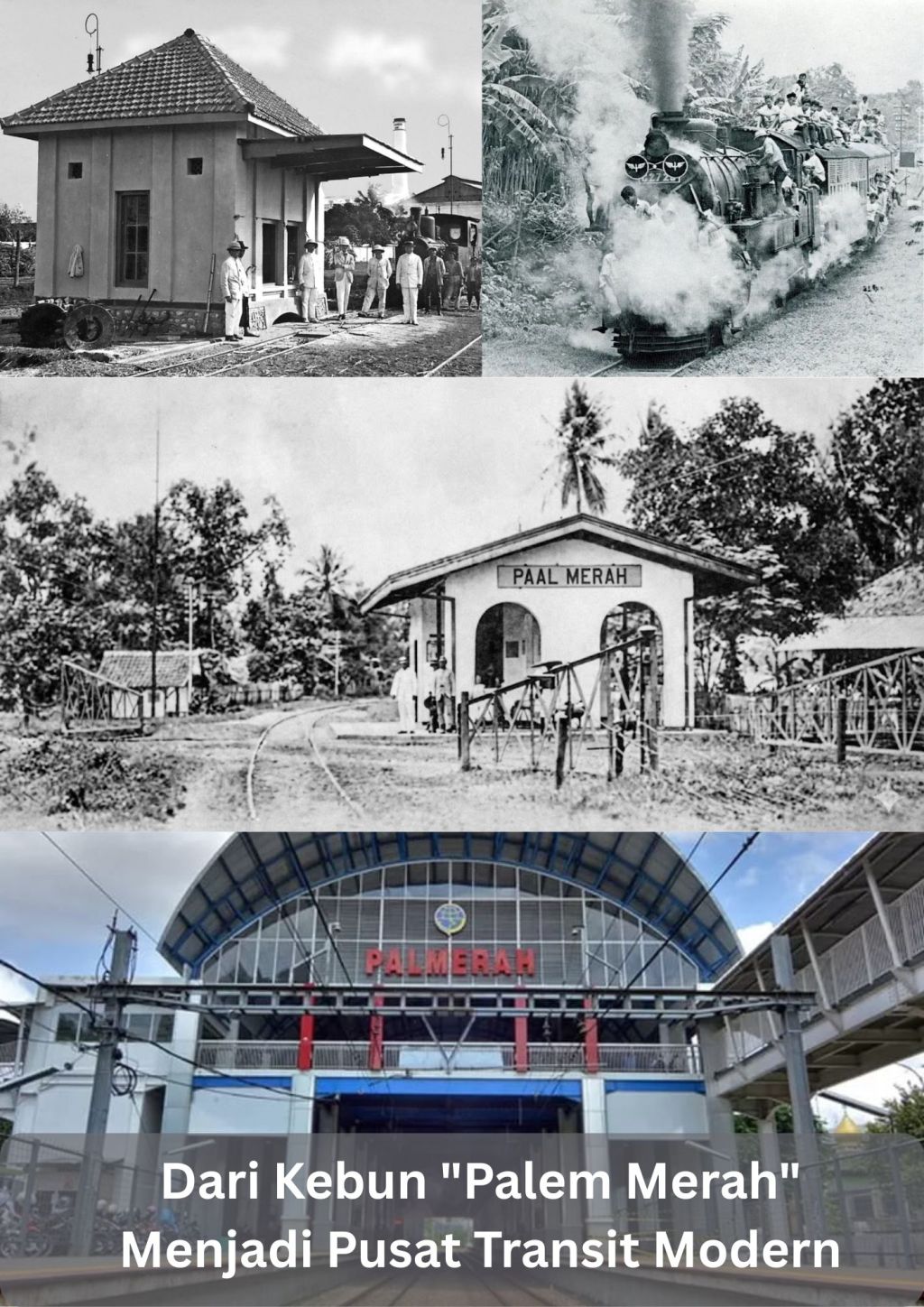
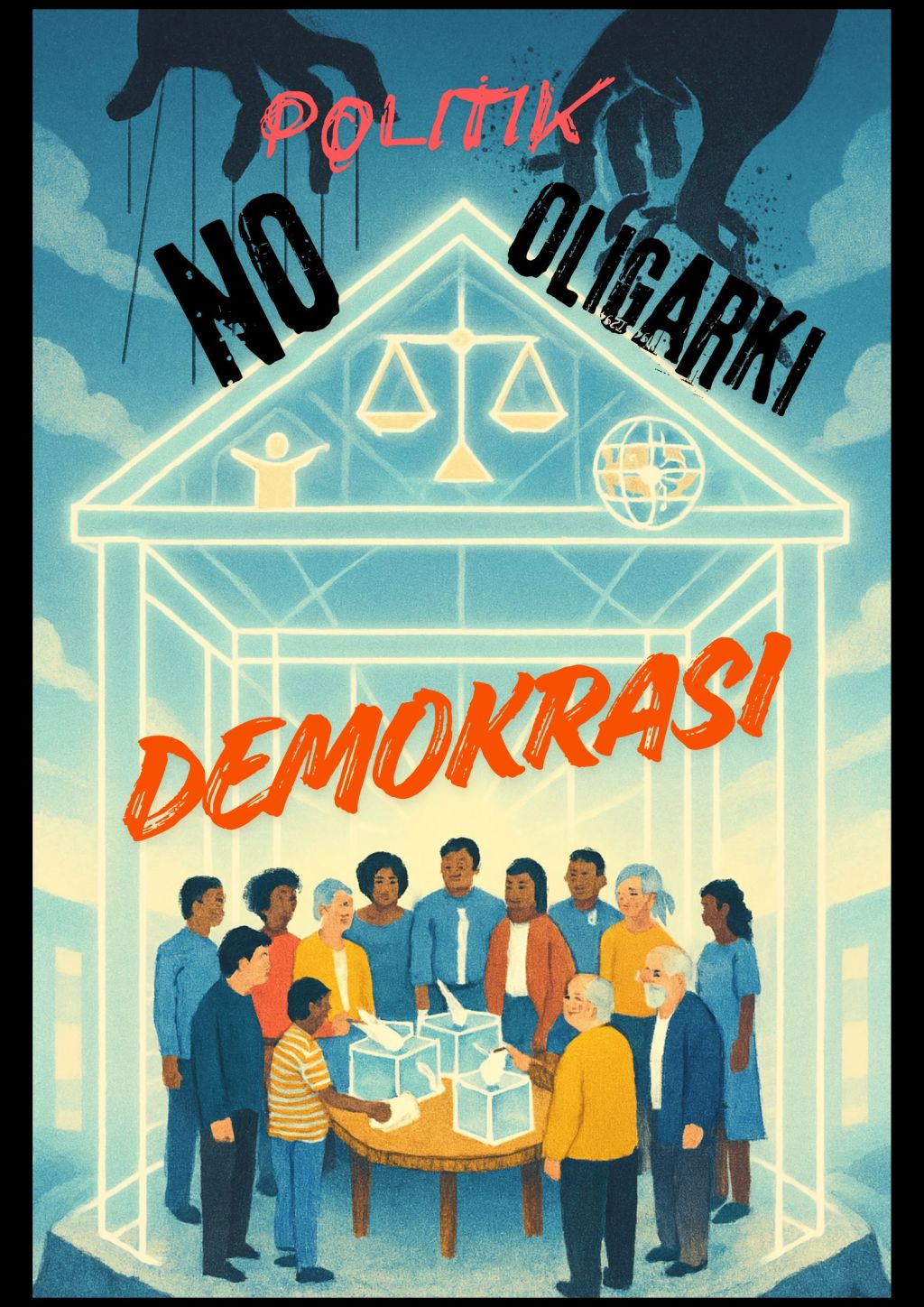




Leave a comment