Rahasia Gelap Kekuasaan dari Pra-Kemerdekaan hingga Sekarang di Era Prabowo
Pendahuluan: Pola Kekuasaan Elitis di Politik Indonesia
Politik Indonesia sejak pra-kemerdekaan hingga era kontemporer terjebak dalam siklus kompetisi kekuasaan. Pertarungan ini terjadi di antara kelompok elit. Militer bertindak sebagai penjaga keamanan dan stabilitas. Oligarki pengusaha mengendalikan sumber daya ekonomi. Agama, khususnya Nahdlatul Ulama/NU, mewakili Islam tradisionalis yang masif.
Pola ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil warisan kolonial, dinamika sosial-budaya yang fragmentasi, dan filosofi kekuasaan yang lebih menekankan hierarki daripada partisipasi rakyat.
Akibatnya, agenda demokrasi substantif dan kesejahteraan rakyat sering terpinggirkan, digantikan oleh konsolidasi kekuasaan yang pragmatis. Penjelasan berikut akan menjelaskan secara historis, sosiologis, budaya, dan filosofis. Selanjutnya, ideologi partai politik saat ini akan dianalisis untuk memahami pola ini.
Perspektif Historis: Dari Kolonialisme hingga Reformasi yang Belum Tuntas
Secara historis, pola kompetisi ini berakar pada era pra-kemerdekaan (1908–1945). Pada masa itu, pergerakan nasional terpecah antara nasionalis sekuler seperti Budi Utomo dan PNI. Ada juga kelompok Islamis, yaitu Sarekat Islam dan cikal bakal NU yang didirikan pada 1926. Selain itu, terdapat kelompok militer awal seperti PETA di bawah Jepang.
Kolonial Belanda memupuk fragmentasi ini untuk mencegah persatuan, sementara Jepang memperkuat militer sebagai alat kontrol.
Saat kemerdekaan (1945), konflik langsung muncul: militer (TNI) menjadi tulang punggung pertahanan melawan Belanda, sementara NU dan kelompok agama lain bersaing dengan nasionalis sekuler dalam Konstituante 1950-an untuk bentuk negara (Islam vs. Pancasila).
Pada Orde Lama (1945–1966), Sukarno memperkenalkan Demokrasi Terpimpin (1959). Pada masa ini, konsep NASAKOM (Nasionalis-Agama-Komunis) diperkenalkan. Militer dan NU (sebagai representasi agama) bersaing dengan PKI untuk pengaruh. Sentralisasi kekuasaan pada Sukarno justru memperlemah partai, memicu kudeta 1965 yang dimenangkan militer di bawah Suharto. Orde Baru (1966–1998) memuncakkan dominasi militer melalui dwifungsi ABRI. Sementara itu, oligarki pengusaha muncul melalui kroni Suharto seperti Liem Sioe Liong. NU diredam tapi tetap berpengaruh di basis pedesaan. Rezim ini menciptakan oligarki militer-bisnis yang mengendalikan ekonomi, dengan agama sebagai alat legitimasi sosial.
Era Reformasi (1998–sekarang) tampak menjanjikan dengan amandemen UUD 1945 yang membatasi militer dan multipartai, tapi pola lama bertahan. Militer mundur dari politik formal, tetapi tetap berpengaruh melalui pensiunan jenderal di partai. Oligarki pengusaha mendominasi dengan cara donasi pemilu. NU (melalui PKB) bersaing dengan kelompok Islam lain untuk isu moral. Krisis 1998 justru memperkuat oligarki baru. Elite bisnis menguasai partai untuk meraih akses kekuasaan. Sementara itu, agenda kesejahteraan seperti pengentasan kemiskinan terhambat oleh korupsi dan patronase. Hingga 2025, di bawah Prabowo-Gibran, konsolidasi ini terlihat pada koalisi besar. Koalisi tersebut menggabungkan militer yang merupakan latar belakang Prabowo. Selain itu, oligarki dengan dukungan pengusaha dan NU dengan dukungan ulama tradisional ikut serta. Oposisi kuat dikorbankan demi stabilitas.
Perspektif Sosiologis: Fragmentasi Masyarakat dan Ketergantungan Elit
Sosiologis, Indonesia sebagai negara agraris-multietnis (dengan 1.300 suku dan 700 bahasa) menciptakan fragmentasi sosial yang dimanfaatkan elit untuk mobilisasi. Militer muncul sebagai “penjaga kesatuan.” Mereka berperan di tengah ancaman disintegrasi seperti DI/TII atau PRRI/Permesta. Sementara itu, oligarki pengusaha mengisi kekosongan ekonomi pasca-kolonial dengan kronisme. Hal ini menciptakan kesenjangan dengan Gini ratio 0,38 pada 2023.
NU mewakili 90 juta umat Islam tradisional di pedesaan. Mereka bersaing karena basis sosialnya yang kuat. Namun, mereka rentan terhadap patronase politik. Kelompok ini sering mendukung kekuasaan demi perlindungan ekonomi (wakaf, pesantren).
Menurut teori Almond-Verba, budaya politik Indonesia bersifat “parokial-subjek.” Dalam budaya ini, rakyat dianggap sebagai objek, bukan aktor. Masyarakat bergantung pada elit untuk distribusi sumber daya. Kompetisi ini menghasilkan “demokrasi oligarkis” (Winters, 2011), di mana kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir kelompok, bukan dispersi untuk kesejahteraan. Hasilnya: 40% kemiskinan pedesaan bertahan, sementara elit saling berebut proyek infrastruktur. Reformasi gagal konsolidasi karena partai lebih fokus rekrutmen elit daripada basis massa, memperburuk ketidakadilan sosial.
Perspektif Budaya: Primordialisme dan Patron-Klien
Budaya Indonesia berbasis gotong royong dan musyawarah. Tradisi ini berasal dari desa Jawa/Minang. Seharusnya mendukung demokrasi inklusif. Namun, justru dimanipulasi menjadi patronase. Ikatan primordial (suku, agama, marga) mendominasi. NU menggunakan jaringan kyai-pesantren untuk mobilisasi suara. Militer mengandalkan loyalitas hierarkis ala feodal. Oligarki pengusaha memanfaatkan budaya “bapak-ism” (figur otoriter sebagai penyelamat). Ini menciptakan budaya politik “pragmatis-transaksional” (Almond), di mana rakyat memilih berdasarkan janji materi, bukan visi jangka panjang.
Warisan kolonial memperkuat ini: Belanda memupuk elite lokal untuk eksploitasi, menciptakan norma “kekuasaan untuk keluarga/kelompok”. Akibatnya, agenda demokrasi seperti pendidikan merata terabaikan. Semua ini demi stabilitas budaya. Sementara itu, kesejahteraan rakyat menjadi alat bargaining. Contohnya adalah subsidi BBM untuk basis NU yang akhirnya dikorupsi oleh oligarki.
Perspektif Filosofis: Kekuasaan sebagai Tujuan, Bukan Sarana
Filosofis, pola ini bertentangan dengan Pancasila yang menekankan kemanusiaan dan keadilan sosial. Namun, pola ini selaras dengan pemikiran Machiavelli ala Indonesia. Kekuasaan dianggap sebagai akhir, bukan sarana. Sukarno’s NASAKOM filosofis mencoba sinkretisme (nasionalisme-agama-komunisme), tapi gagal karena hierarki kekuasaan (militer vs. agama). Suharto’s Orde Baru filosofis membenarkan otoritarianisme sebagai “demokrasi Pancasila”, di mana militer-ekonomi jadi “tubuh organik” negara, mengorbankan individualisme demokratis.
Aristoteles’ oligarki (kekuasaan segelintir kaya) terwujud di sini: elit mengklaim mewakili rakyat, tapi filosofisnya egois (kepentingan pribadi > umum). Demokrasi Indonesia jadi “procedural” (pemilu rutin). Demokrasi ini bukan substantif (kesejahteraan). Filosofi kekuasaan masih feodal-kolonial. Raja (presiden) dan vassal (elit) bersaing, sementara rakyat tetap sebagai subjek. Ini menjelaskan mengapa reformasi 1998 tak ubah akar: filosofi belum bergeser ke Rawls’ keadilan distributif.
Ideologi Partai Politik Saat Ini: Pancasila Pragmatis dan Konsolidasi Kekuasaan
Semua partai di Indonesia wajib berideologi Pancasila sejak 1985 (Asas Tunggal). Namun, implementasinya pragmatis. Ideologi jadi kulit luar, sementara intinya adalah perebutan kekuasaan. Saat ini (2025), partai-partai besar didominasi oligarki internal, di mana ideologi sekunder dibanding koalisi elektoral.
Konsolidasi partai berkuasa terjadi seperti Koalisi Indonesia Maju di era Prabowo. Hal ini menghasilkan situasi sekarang: kebijakan pro-bisnis (oligarki), dukungan militer (stabilitas), dan akomodasi NU (legitimasi moral). Namun, ada minim agenda rakyat seperti reformasi agraria.
Berikut tabel ideologi utama partai besar (berdasarkan AD/ART dan praktik 2024–2025):
| Partai Politik | Ideologi Utama | Karakteristik Praktik | Peran dalam Kompetisi Elit |
|---|---|---|---|
| PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) | Nasionalisme Pancasila (warisan Sukarno) | Fokus gotong royong, populisme kiri-tengah; kuat di basis Jawa. | Elite nasionalis; saingan oligarki via program sosial, tapi pragmatis dalam koalisi. |
| Golkar (Partai Golongan Karya) | Fungsionalisme Pancasila (ekonomi pembangunan) | Pragmatis, pro-bisnis; warisan Orde Baru. | Jembatan oligarki-militer; konsolidasi kekuasaan via kroni pengusaha. |
| Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) | Nasionalisme populis | Anti-korupsi retoris, tapi militeristik. | Kuat militer (Prabowo); kompetisi kekuasaan via figur karismatik. |
| PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) | Islam tradisionalis (NU) | Moderat, inklusif; fokus kesejahteraan pedesaan. | Representasi NU; saingan agama lain, tapi sering jadi penyeimbang koalisi. |
| NasDem | Nasionalisme demokratis | Pro-demokrasi, tapi elite bisnis dominan. | Oligarki pengusaha; ideologi fleksibel untuk koalisi. |
| PAN (Partai Amanat Nasional) | Islam modernis | Konservatif, pro-pasar. | Kompetisi agama; bergantung dukungan ulama non-NU. |
| PKS (Partai Keadilan Sejahtera) | Islam fundamentalis (inspirasi Ikhwanul Muslimin) | Anti-korupsi, syariah ringan. | Saingan NU di basis urban; ideologi kuat tapi minoritas. |
| PPP (Partai Persatuan Pembangunan) | Islam tradisional (gabungan NU-Masyumi lama) | Konservatif, pro-ekonomi syariah. | Lemah pasca-pembelahan; sering jadi pion oligarki. |
Ideologi ini “minus ideologi” (pragmatis), di mana partai berganti posisi oposisi-berkuasa tanpa konsistensi, demi konsolidasi (koalisi 80% kursi DPR). Hasilnya: kebijakan seperti UU Cipta Kerja (2020) pro-oligarki, sementara demokrasi stagnan karena politik uang dan dinasti. Untuk perubahan, butuh penguatan ideologi via kaderisasi dan batas masa jabatan elite.
Kesimpulan: Menuju Demokrasi yang Lebih Substantif
Pola Militer-Oligarki-Agama-NU ini bertahan karena fondasi historis kolonial, sosiologis fragmentasi, budaya patronase, dan filosofi kekuasaan elitis. Partai saat ini, meski Pancasila, memperkuatnya via konsolidasi pragmatis. Solusi: reformasi partai (ideologi wajib, transparansi donasi) dan pendidikan politik untuk ubah rakyat dari objek jadi subjek. Tanpa itu, Indonesia tetap negara “demokrasi oligarkis” di mana kekuasaan berputar, tapi kesejahteraan rakyat mandek.





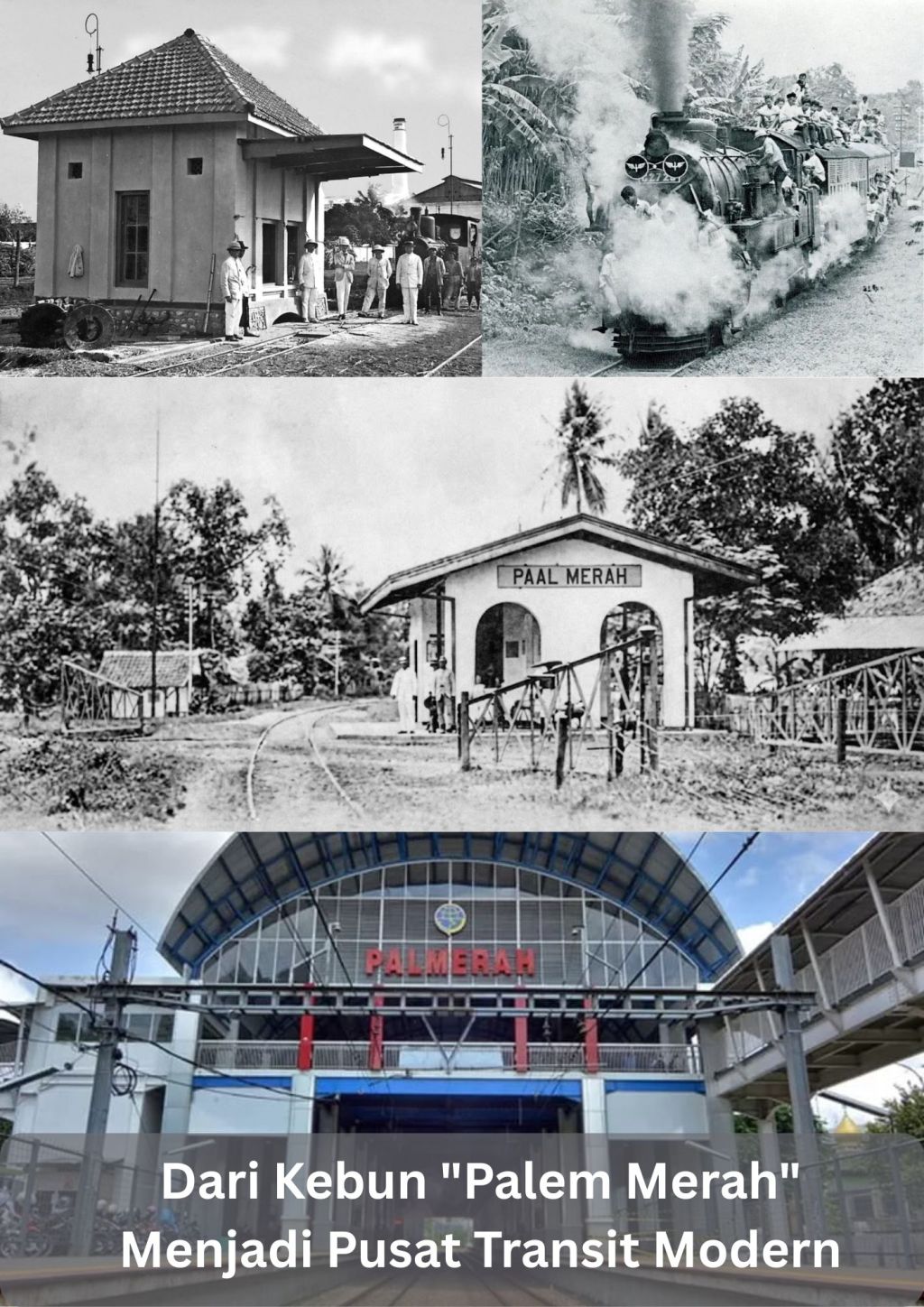
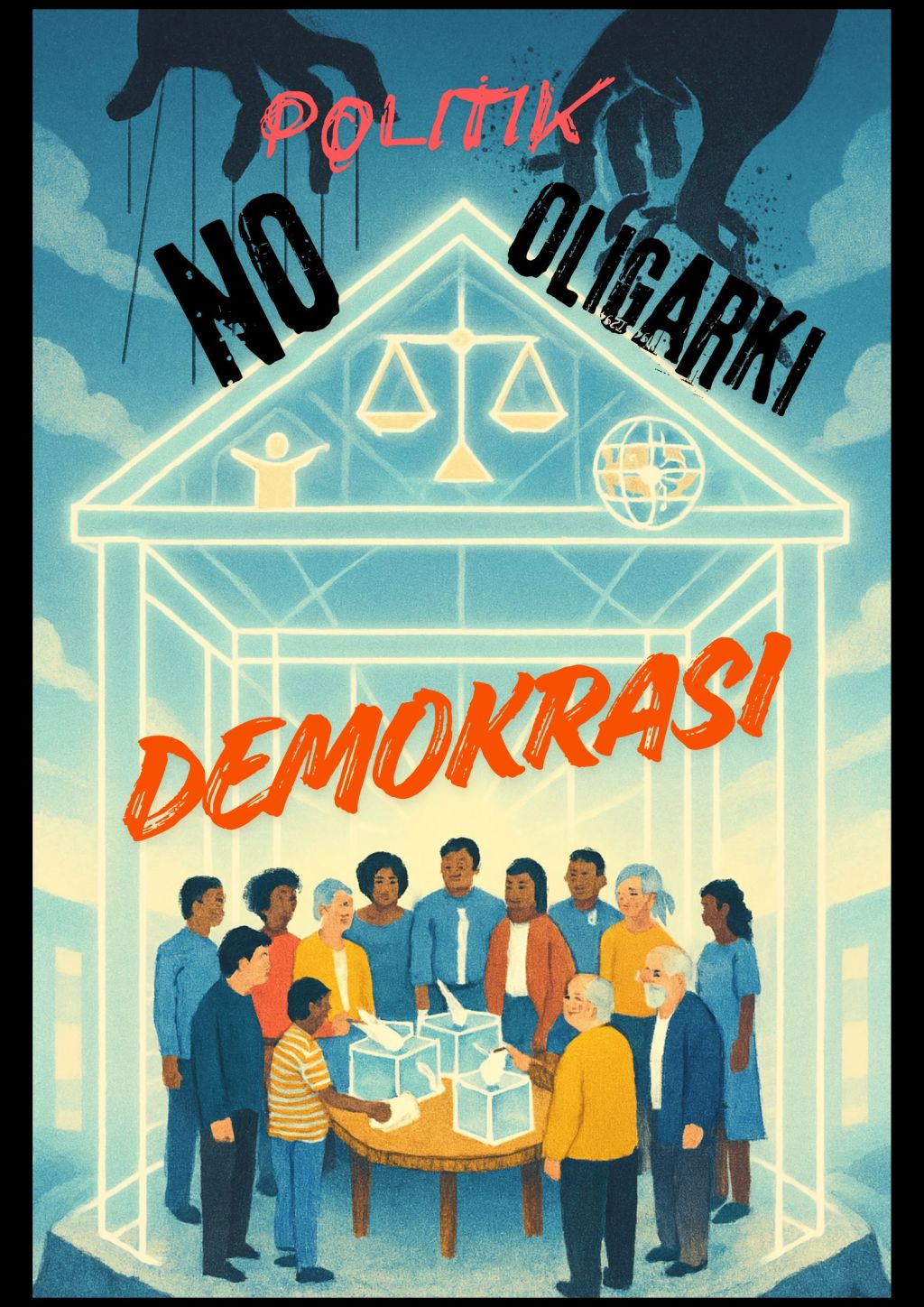




Leave a comment