Indonesia, dengan Pancasila sebagai fondasi ideologinya, telah lama berjuang untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Namun, di tengah tantangan globalisasi, ketimpangan ekonomi, dan polarisasi politik Demokrasi Pancasila mengalami kegagalan.
Politik Indonesia sejak pra-kemerdekaan hingga era kontemporer sering terjebak dalam siklus kompetisi kekuasaan. Kompetisi ini terjadi antara kelompok elit. Militer berperan sebagai penjaga keamanan dan stabilitas. Oligarki pengusaha mengendalikan sumber daya ekonomi. Agama, khususnya Nahdlatul Ulama, juga berperan penting.
Pola ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil warisan kolonial dan dinamika sosial-budaya yang fragmentasi. Selain itu, filosofi kekuasaan lebih menekankan hierarki daripada partisipasi rakyat. Akibatnya, agenda demokrasi substantif dan kesejahteraan rakyat sering terpinggirkan, digantikan oleh konsolidasi kekuasaan yang pragmatis.
Awal Kemerdekaan Indonesia
Pada akhir 1950-an, Indonesia menghadapi instabilitas politik akibat konflik antarpartai. Pemberontakan regional seperti PRRI/Permesta turut berkontribusi. Krisis ekonomi yang parah, termasuk inflasi tinggi dan kekurangan pangan, juga menjadi tantangan. Sukarno melihat sistem Demokrasi Parlementer gagal menjaga stabilitas.
Sukarno mengusulkan Demokrasi Terpimpin sebagai alternatif. Dia menganggapnya lebih sesuai dengan “jiwa bangsa Indonesia.” Menurutnya, sistem ini berbasis pada musyawarah-mufakat, yang merupakan salah satu prinsip Pancasila. Namun, dalam praktiknya, sistem ini cenderung otoriter. Ini dianggap menyimpang dari sila ke-4 (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permenangan/Permusyawaratan).
Sukarno memperkuat posisinya sebagai “Pemimpin Besar Revolusi” dalam Demokrasi Terpimpin. Dia memiliki kekuasaan yang hampir tidak terbatas. Sukarno bahkan membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Dia menggantinya dengan DPR-GR yang anggotanya ditunjuk. Hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi Pancasila, yang menekankan kedaulatan rakyat.
Sukarno memperkenalkan konsep NASAKOM (Nasionalisme, Agama, Komunisme) untuk memadukan berbagai kekuatan politik. Namun, dalam praktiknya, ia cenderung mendekati Partai Komunis Indonesia (PKI), yang menyebabkan ketegangan dengan kelompok agama dan militer. Pendekatan ini dianggap menyimpang dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini memicu polarisasi ideologis. Polarisasi ini mengancam kesatuan nasional.
Sukarno sering menggunakan Pancasila sebagai alat retoris untuk melegitimasi kebijakannya. Namun, interpretasinya terhadap Pancasila bersifat subjektif. Interpretasi tersebut disesuaikan dengan visi revolusionernya.
Sukarno, dengan karismanya, memposisikan dirinya sebagai penutur utama ideologi bangsa. Ia menganggap dirinya sebagai perwujudan “suara rakyat,” yang membuatnya merasa berhak menafsirkan Pancasila sesuai visinya.
Selama Orde Baru (1966–1998), Suharto, sebagai presiden melenceng dari nilai-nilai Pancasila meskipun ia telah menyaksikan dampak penyimpangan pada masa Sukarno.
Suharto membangun sistem pemerintahan yang sangat sentralistis dan otoriter, dengan militer (ABRI) sebagai tulang punggung kekuasaan melalui konsep “Dwifungsi ABRI.” Meskipun Orde Baru mengklaim menegakkan Pancasila melalui “Pancasila Demokrasi,” pada prakteknya, sila ke-4 diabaikan. (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan). Pemilu diatur sedemikian rupa. Golkar selalu menang. DPR kehilangan fungsi pengawasan. Kebebasan berpendapat dibatasi melalui represi terhadap pers dan oposisi. Ini bertentangan dengan semangat demokrasi rakyat dalam Pancasila.
Program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) menjadi wajib. Tujuannya adalah formalitas untuk memastikan loyalitas terhadap rezim. Program ini tidak bertujuan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara substantif. Pancasila kehilangan makna aslinya. Hal ini terutama terjadi pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Sosial. Ideologi tersebut lebih digunakan untuk kontrol sosial daripada pedoman moral.
Meskipun Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur, praktik KKN merajalela. Suharto memberikan keistimewaan kepada keluarga dan kroni dalam bisnis, seperti proyek-proyek besar yang dikuasai oleh anak-anaknya atau kelompok Cendana. Kekayaan terkonsentrasi pada segelintir elit, sementara kesenjangan sosial meningkat.
Orde Baru sering menggunakan kekerasan untuk menekan perbedaan pendapat, seperti dalam kasus Tanjung Priok (1984), Lampung (1989), atau penanganan di Timor Timur dan Aceh. Tindakan ini melanggar sila ke-2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), karena mengorbankan hak asasi manusia demi stabilitas politik. Suharto, yang melihat instabilitas pada masa Sukarno, memprioritaskan ketertiban, tetapi caranya justru menimbulkan ketidakadilan.
Suharto bertekad menciptakan stabilitas untuk pembangunan ekonomi. Namun, pendekatan ini mengorbankan aspek demokrasi dan musyawarah dalam Pancasila. Kebijakan seperti “floating mass” mengurangi partisipasi politik rakyat di luar pemilu. Pembubaran organisasi politik dianggap bertentangan dengan semangat kerakyatan dan musyawarah.
Meskipun Reformasi ditandai dengan semangat demokratisasi dan desentralisasi, penyimpangan dari Pancasila tetap terjadi karena berbagai faktor. Berikut adalah penjelasan penyebabnya untuk setiap periode kepresidenan:
Di era Reformasi (1998–sekarang), ada persepsi bahwa beberapa kebijakan atau praktik pemerintahan menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Ini berlangsung dari masa kepresidenan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hingga Joko Widodo (Jokowi). Kebijakan tersebut dianggap melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Meskipun Reformasi ditandai dengan semangat demokratisasi dan desentralisasi, penyimpangan dari Pancasila tetap terjadi karena berbagai faktor. Berikut adalah penjelasan penyebabnya untuk setiap periode kepresidenan:
Abdurrahman Wahid (1999–2001)
Gus Dur dikenal dengan pendekatan pluralis dan inklusif. Pendekatan ini sejalan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Namun, kebijakannya seperti usulan mencabut larangan komunisme dan hubungan diplomatik dengan Israel memicu polarisasi, yang dianggap mengganggu sila Persatuan Indonesia. Ketegangan dengan DPR dan militer juga memperlemah stabilitas, sehingga dianggap tidak mendukung musyawarah (sila ke-4).
Gus Dur sering membuat keputusan impulsif. Tindakan seperti memecat pejabat tanpa koordinasi yang jelas dianggap tidak mencerminkan hikmat kebijaksanaan (sila ke-4). Hal ini memicu konflik politik dan akhirnya lengser melalui impeachment, yang menunjukkan lemahnya musyawarah dalam menyelesaikan konflik.
Meskipun Gus Dur dikenal jujur secara pribadi, kasus seperti Buloggate dan Bruneigate memunculkan persepsi adanya praktik korupsi di lingkarannya. Hal ini bertentangan dengan sila Keadilan Sosial.
Megawati Soekarnoputri (2001–2004)
Megawati lamban menangani kasus pelanggaran HAM berat. Kasus tersebut meliputi kasus Tanjung Priok atau Timor Timur. Hal ini bertentangan dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Fokusnya pada stabilitas politik membuat isu keadilan kurang diprioritaskan.
Meskipun Reformasi menjanjikan pemberantasan KKN, praktik korupsi dan nepotisme masih terjadi, terutama dalam pengangkatan pejabat dan proyek pemerintah. Hal ini melanggar sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pemerintah menggunakan pendekatan militer untuk menangani konflik di Aceh (operasi militer 2003). Pendekatan ini dianggap kurang mencerminkan kemanusiaan dan musyawarah. Metodenya lebih mengedepankan kekerasan daripada dialog.
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (2004–2014)
Meskipun SBY mempromosikan pemberantasan korupsi melalui KPK, banyak kasus korupsi melibatkan pejabat tinggi Partai Demokrat. Koalisi pemerintahannya juga turut serta dalam kasus korupsi seperti kasus Hambalang. Ini bertentangan dengan sila Keadilan Sosial, karena rakyat tidak merasakan keadilan ekonomi secara merata.
Pertumbuhan ekonomi di era SBY cukup tinggi, tetapi distribusi kekayaan tidak merata, dengan kesenjangan antara kota dan desa serta antara kaya dan miskin semakin lebar. Ini menyimpang dari sila ke-5. Meskipun ada kemajuan demokratisasi, kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan aktivis Munir tidak terselesaikan secara tuntas. Hal ini menunjukkan lemahnya implementasi sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Untuk menjaga stabilitas, SBY membentuk koalisi besar. Koalisi ini sering kali mengorbankan prinsip ideologis demi kepentingan politik. Akibatnya, musyawarah dalam sila ke-4 lebih bersifat transaksional.
Joko Widodo (Jokowi) (2014–2024)
Jokowi dikenal dengan proyek infrastruktur besar. Namun, banyak proyek dianggap lebih menguntungkan investor atau korporasi. Contohnya adalah proyek IKN (Ibu Kota Nusantara). Dampaknya, seperti penggusuran atau marginalisasi masyarakat adat, dianggap melanggar sila Keadilan Sosial dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Meskipun Jokowi menjanjikan pemerintahan yang bersih, kasus korupsi tetap ada. Dugaan politik dinasti juga muncul. Contohnya termasuk pencalonan anak dan menantunya di pilkada. Ini dianggap bertentangan dengan sila ke-4 dan ke-5 karena mengesampingkan meritokrasi dan keadilan. Beberapa kebijakan, seperti UU ITE atau penanganan demonstrasi ada yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Kebijakan ini bertentangan dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Ketergantungan pada investasi asing, terutama dari Tiongkok, untuk proyek-proyek besar dianggap mengorbankan kedaulatan ekonomi. Hal ini dapat dipandang menyimpang dari semangat sila Keadilan Sosial dan Persatuan Indonesia.
Era Jokowi ditandai dengan polarisasi sosial, terutama terkait politik identitas berbasis agama. Meskipun Jokowi berupaya menjaga pluralisme, penanganan isu-isu sensitif seperti kasus Ahok atau kelompok Islam radikal dianggap kurang tegas. Hal ini memengaruhi sila Persatuan Indonesia.
Penyimpangan dari Pancasila di setiap era akibat dari tantangan ambisi kekuasaan, dan tekanan eksternal seperti globalisasi.
Pancasila, sebagai ideologi luhur, sering kali tidak terimplementasi secara utuh. Hal ini terjadi karena faktor kepemimpinan, kelemahan sistem, dan dinamika sosial-politik. Tantangan utama adalah menjadikan Pancasila sebagai panduan praktis. Jangan biarkan itu menjadi sekadar simbol atau alat politik.
Kepemimpinan Sukarno (Demokrasi Terpimpin) dan Suharto (Orde Baru) ditandai dengan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Era Reformasi (Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, dan Jokowi) juga mengalami hal serupa. Penyebabnya adalah berbagai faktor yang dipengaruhi oleh konteks politik, sosial, dan ekonomi masing-masing era.
Konsentrasi Kekuasaan dan Otoritarianisme
Sukarno dan Suharto sama-sama memusatkan kekuasaan, dengan Sukarno melalui Demokrasi Terpimpin dan Suharto melalui sistem otoriter Orde Baru. Keduanya mengesampingkan sila ke-4. Di era Reformasi, meskipun demokrasi lebih terbuka, praktik politik pragmatis melemahkan semangat demokrasi. Contohnya adalah koalisi transaksional (SBY) ataupun politik dinasti (Jokowi). Ini tetap melemahkan semangat demokrasi dan keadilan sosial.
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
KKN menjadi masalah berulang di setiap era. Pada masa Sukarno, krisis ekonomi memicu korupsi sistemik. Di Orde Baru, KKN merajalela di kalangan keluarga dan kroni Suharto. Di era Reformasi, meskipun ada upaya pemberantasan melalui KPK, korupsi tetap ada. Contohnya adalah kasus-kasus di era SBY dan dugaan nepotisme di era Jokowi. Hal ini secara konsisten melanggar sila ke-5
Pelanggaran HAM dan Kemanusiaan
Setiap era memiliki catatan pelanggaran HAM yang bertentangan dengan sila ke-2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab). Sukarno menggunakan kekerasan untuk menekan pemberontakan, Suharto melakukan represi di Aceh, Timor Timur, dan lainnya, sementara di era Reformasi, kasus-kasus seperti pembunuhan Munir (SBY) atau penggusuran terkait proyek infrastruktur (Jokowi) menunjukkan lemahnya penegakan keadilan kemanusiaan.
Polarisasi dan Ancaman Persatuan
Polarisasi sosial dan politik menjadi tantangan di setiap periode. Sukarno memicu konflik ideologis melalui NASAKOM. Suharto menekan kelompok agama dan ideologi lain. Di era Reformasi, politik identitas berbasis agama atau etnis, terutama di era Jokowi, mengancam sila ke-3 (Persatuan Indonesia). Ketidakmampuan menjaga harmoni antarkelompok sering kali melemahkan semangat persatuan.
Penyalahgunaan Pancasila sebagai Alat Politik
Pancasila sering digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan daripada pedoman moral. Sukarno menafsirkan Pancasila secara subjektif untuk visi revolusionernya. Suharto memaksakan P4 untuk kontrol sosial. Di era Reformasi, Pancasila kadang hanya menjadi jargon tanpa implementasi substansial. Ini terutama terlihat dalam menegakkan keadilan sosial dan demokrasi.
Pengaruh Ekonomi dan Globalisasi
Krisis ekonomi di era Sukarno sering kali mengorbankan sila Keadilan Sosial. Ketergantungan pada investasi asing di era Suharto serta Reformasi (terutama Jokowi) juga memiliki efek yang sama. Kebijakan ekonomi yang lebih menguntungkan elit atau investor asing menyebabkan kesenjangan sosial, yang bertentangan dengan semangat Pancasila untuk kesejahteraan rakyat.
Transisi dan Tantangan Demokrasi Setiap era menghadapi tantangan dalam menerapkan demokrasi sesuai Pancasila. Sukarno dan Suharto gagal karena otoritarianisme. Sementara di era Reformasi, meskipun demokrasi lebih terbuka, kelemahan institusional menghambat penerapan Demokrasi Pancasila secara utuh. Pragmatisme politik dan polarisasi sosial juga menjadi hambatan.
Era Prabowo (2024 – 2029) Konsolidasi partai berkuasa berideologi Pancasila Koalisi Indonesia Maju bersambung,,



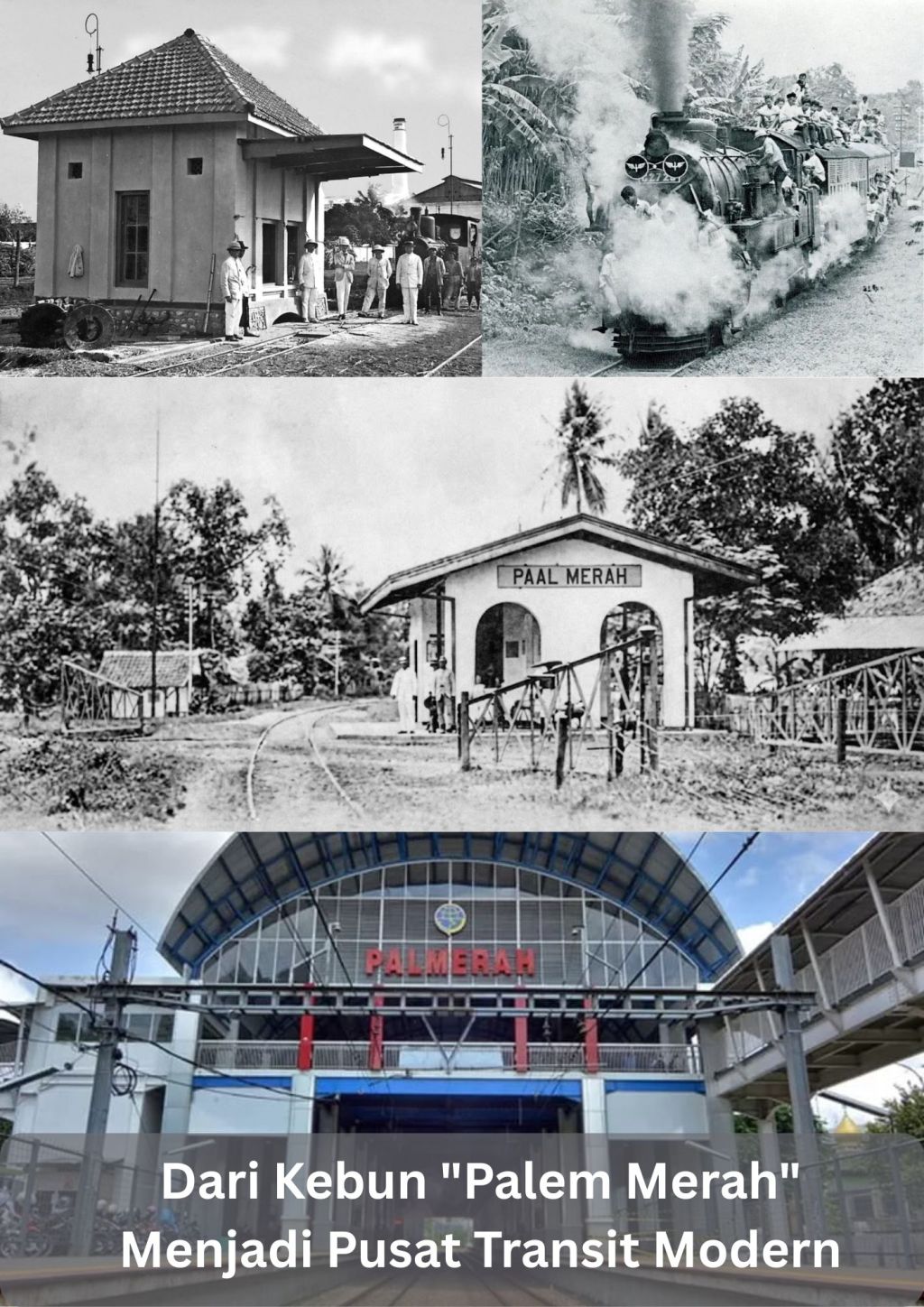
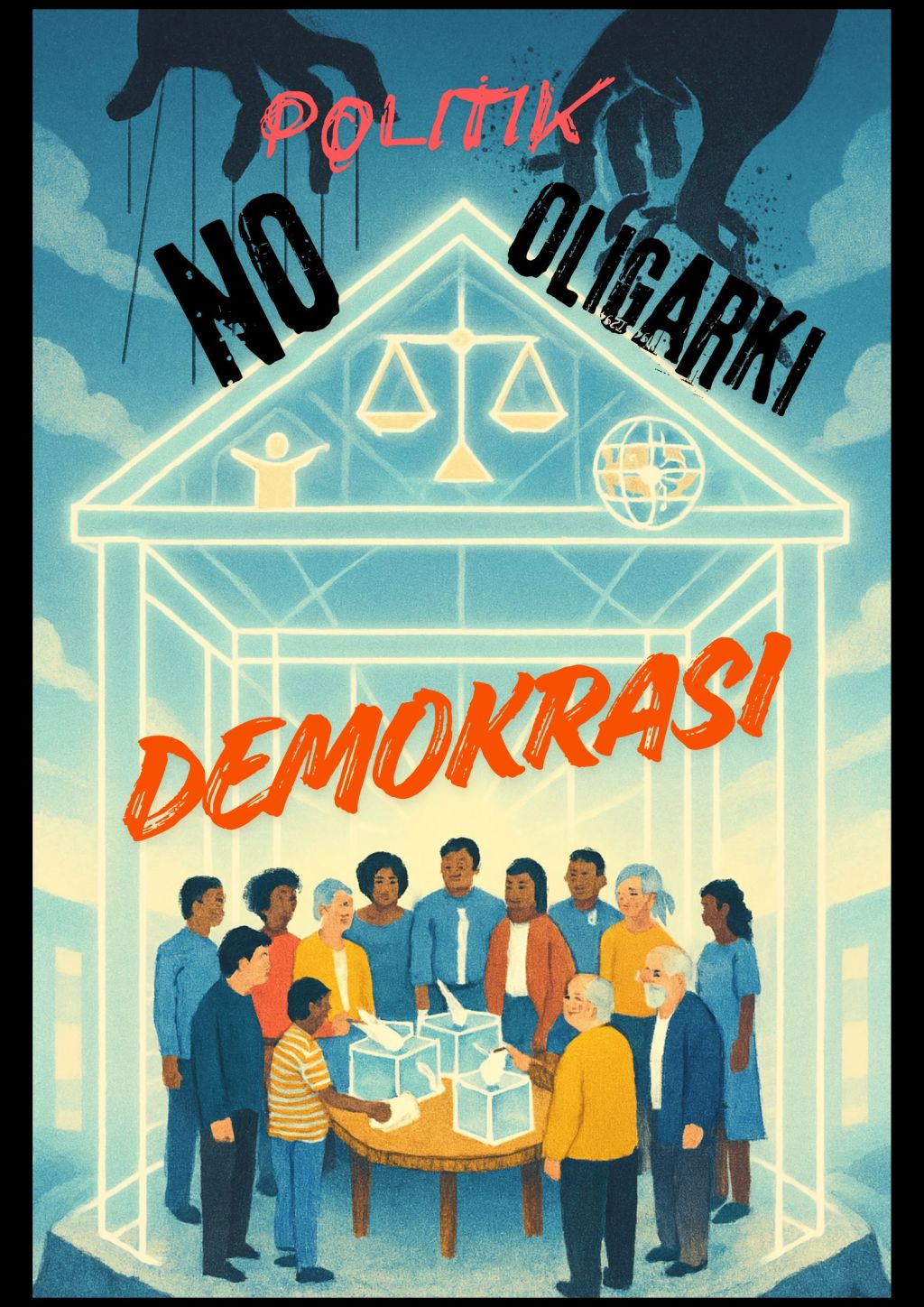






Leave a comment