Pada 20 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih 2024-2029. Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih 2024-2029. Prabowo memenangkan pemilu dengan 58,59 persen suara. Itu setara dengan sekitar 96 juta pemilih. Kemenangan satu putaran ini menandai puncak perjalanan panjang Prabowo. Ia adalah mantan jenderal yang dua kali kalah dari Joko Widodo. Namun, di balik sorak sorai pendukung, ada sketsa konsolidasi kekuasaan Jokowi yang mengubah wajah demokrasi Indonesia.

Konsolidasi kekuasaan Jokowi dimulai sejak periode kedua kepemimpinannya. Koalisi Indonesia Maju menguasai 70 persen kursi DPR, menyatukan Gerindra, Golkar, hingga Demokrat. “Jokowi adalah mesin elektoral,” kata Ujang Komarudin dari Indonesia Political Review. Langkah krusial terjadi pada 2019, saat Jokowi merangkul Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, mengubah rival menjadi sekutu.
Puncaknya adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengizinkan Gibran, putra Jokowi, maju sebagai cawapres meski berusia 36 tahun. Putusan ini, dipimpin ipar Jokowi, Anwar Usman, memicu tuduhan politik dinasti. Demonstrasi mahasiswa dengan spanduk “Tolak Dinasti” mewarnai Jakarta, tapi tak mengubah hasil. “Ini kemunduran demokrasi,” kata Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia.
Penyalahgunaan aparatur negara memperkuat kemenangan. Bawaslu mencatat 1.200 kasus pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri. Bansos Rp 500 triliun, disalurkan saat kampanye, diduga menjadi alat politik. Di Jawa Tengah, distribusi beras bansos dikaitkan dengan Prabowo-Gibran, membantu mereka menang di 36 dari 38 provinsi. Media sosial juga dimanfaatkan: kampanye “Gemoy” Prabowo di TikTok dan Instagram mengubah citranya menjadi ramah, sementara kritik terhadap Jokowi diredam. Polisi menangkap 50 aktivis atas tuduhan “provokasi” daring pada 2023.
Sekarang Kekuatan Jokowi ada di Koalisi Indonesia Maju. KIM yang menjadi tulang punggung pemerintahan Prabowo berhasil mempersatukan hampir seluruh partai besar di parlemen. Ini menciptakan stabilitas politik yang belum pernah terjadi sejak era Soeharto — namun juga mengaburkan batas antara koalisi dan oposisi.
Kekuatan politik bernaung di bawah ideologi “Pancasila” versi negara. Sekarang, keseimbangan politik tampak lebih seperti sistem hegemonic coalition.
Partai-partai di DPR kini berlomba menjadi bagian dari kekuasaan, bukan untuk menantangnya.
Yang kita lihat bukan lagi politik demokrasi, tetapi politik korporasi. “Demokrasi tetap hidup secara prosedural, tapi kehilangan daya tawarnya secara substantif.”
Pusat pengambilan keputusan kini makin terkonsentrasi di tangan presiden dan lingkaran elite ekonomi-militer di sekitarnya. Politik musyawarah digantikan dengan politik kesepakatan elitis — di mana kepentingan rakyat sering kali muncul hanya sebagai retorika.
Dari sisi ekonomi, arah kebijakan pemerintahan Prabowo menunjukkan kesinambungan dari era Jokowi: infrastruktur besar, hilirisasi industri, dan digitalisasi ekonomi. Namun, pendekatan yang sangat pro-bisnis memperkuat dominasi oligarki.
Selain itu, kehadiran militer dan pensiunan perwira dalam jajaran BUMN serta proyek strategis nasional menunjukkan kecenderungan baru. Ini adalah ekonomi berbasis keamanan. Dalam sistem ini, stabilitas menjadi justifikasi untuk intervensi struktural.
Dukungan militer terhadap Prabowo bukan sekadar simbol. Ia merepresentasikan kembalinya militer dalam orbit kekuasaan sipil — bukan melalui kudeta, tapi lewat kooptasi politik dan ekonomi.
Dukungan Nahdlatul Ulama menjadi faktor kunci dalam membangun legitimasi sosial pemerintahan ini. Dalam lanskap sosial yang terfragmentasi oleh media digital dan politik identitas, NU berperan sebagai penyangga moral dan sosial.
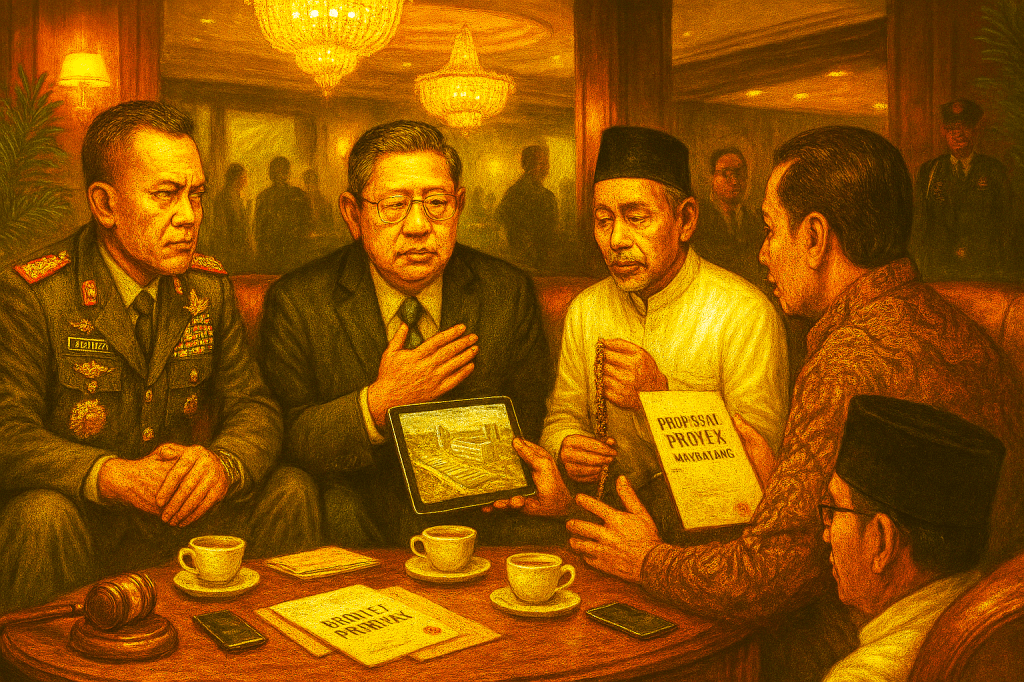
Namun, akomodasi ini juga membawa konsekuensi politis. NU kini bukan hanya mitra spiritual negara, tetapi bagian dari mesin kekuasaan itu sendiri. Dengan masuknya kader-kader NU dalam kabinet dan posisi strategis, batas antara otoritas moral dan kekuasaan politik kian kabur.
Bagi sebagian kalangan muda, terutama di perkotaan, situasi ini menimbulkan dilema baru. Stabilitas sosial dijaga. Namun, ada risiko membungkam diskursus kritis dan keberagaman pandangan.
Program “stabilitas nasional” kini beririsan erat dengan agenda keamanan digital dan pengawasan informasi. Di balik narasi keamanan siber, muncul kekhawatiran akan meningkatnya kontrol negara terhadap opini publik, terutama di media sosial.
Aparat keamanan, terutama TNI dan Polri, semakin aktif dalam ranah non-militer: penanganan bencana, proyek infrastruktur, hingga pengamanan investasi. Semua ini memperluas peran militer di ranah sipil. Ini adalah pola yang mengingatkan pada masa Dwifungsi ABRI. Namun, itu dikemas dengan wajah modern.
Era Prabowo menandai fase baru bagi Indonesia. Ini adalah sebuah pemerintahan dengan stabilitas politik tinggi. Pemerintahan ini memiliki dukungan militer kuat dan legitimasi sosial berbasis agama.
Namun, stabilitas ini datang dengan risiko membekukan dinamika demokrasi dan mengerdilkan partisipasi rakyat. Indonesia kini menjadi negara stabil tapi elitis.
Masa Depan Pemerintahan Prabowo
- 2026: Represi meningkat perlahan disertai meningkatnya tekanan ekonomi dan sosial (harga pangan, korupsi, pengangguran).
- 2027: Retakan elite dan meningkatnya protes mahasiswa, buruh, dan kelompok moral.
- 2028: Momentum Politik REVOLUSI Bubarkan Partai Politik Oligarki atau Berlanjut
- 2029: Harapan runtuhnya Oligarki dengan kekuatan Rakyat dan Reformasi Total Politik
Berikut faktor-faktor yang dapat memperbesar kemungkinan scenario Krisis Sosial dan Ledakan Politik di Indonesia pada periode 2025–2029. Faktor Politik – Ekonomi – Sosial – Hukum dan HAM
Faktor Politik: Monopoli Politik yang Terlalu Tertutup. Ketika seluruh partai besar bergabung dalam satu koalisi, tidak ada oposisi yang kredibel. Publik kehilangan saluran politik untuk menyalurkan kekecewaan. → Efek: Ketidakpuasan tidak muncul di parlemen, tetapi di jalanan. → Indikator: Meningkatnya aksi mahasiswa, serikat buruh, dan kelompok masyarakat sipil di luar sistem.
Fragmentasi di Dalam: Dalam sistem yang terkonsentrasi, ancaman sering datang dari dalam. Persaingan antara faksi militer, bisnis, dan agama dalam lingkar kekuasaan dapat memicu retakan internal. → Efek: kebijakan jadi tidak konsisten, muncul krisis kepercayaan publik.
Krisis Legitimasi Moral: Lembaga agama dianggap terlalu dekat dengan kekuasaan. Hal ini membuat masyarakat religius dapat berbalik arah. → Efek: kehilangan basis moral akan menggerogoti stabilitas sosial yang dibangun dengan simbol keagamaan.
Faktor Ekonomi: · Kesenjangan Kaya-Miskin yang Melebar. Ketika ekonomi tumbuh, tapi hanya dinikmati kelompok korporasi besar dan elite politik, rasa ketidakadilan meningkat. → Efek: Rasa “tertinggal” di kalangan muda muncul di kalangan pekerja informal. Hal ini bisa memicu gerakan ekonomi-politik baru. Contohnya adalah gerakan seperti “Occupy” atau “Reformasi Jilid II”.
Stagnasi Ekonomi Rakyat UMKM, buruh, dan petani tetap terjebak dalam biaya hidup tinggi dan akses modal yang sempit. → Efek: muncul kemarahan sosial di tingkat lokal (terutama di daerah industri dan pertambangan).
Korupsi dan Nepotisme yang Kasat Mata: Proyek besar dan kebijakan publik dikuasai jaringan oligarki dan militer. Masyarakat akan melihat “pembangunan” sebagai simbol ketidakadilan.
→ Efek: kepercayaan terhadap negara menurun drastis, memicu tuntutan moral dan protes sosial.
Tekanan Inflasi dan Pengangguran Muda: Kombinasi inflasi pangan, pengangguran sarjana, dan kemerosotan daya beli. Ini berpotensi menjadi katalis yang sangat cepat untuk gejolak sosial. → Indikator: naiknya aktivitas ekonomi informal dan unjuk rasa buruh.
Faktor Sosial:
- Kejenuhan Generasi Muda terhadap Politik Formal. Saat anak muda merasa tidak punya ruang di sistem politik formal, mereka akan mencari ruang ekspresi lain. Mereka melakukannya melalui media sosial, seni, atau aktivisme digital. → Efek: lahirnya digital populism — gerakan massa spontan berbasis media daring yang sulit dikendalikan negara.
- Krisis Moral di Lembaga Agama dan Sosial. Ketika lembaga keagamaan yang selama ini menjadi “penyangga moral” ikut terseret politik kekuasaan dan ekonomi, masyarakat bawah kehilangan panutan. → Efek: muncul “gerakan moral baru” di luar arus utama. Gerakan ini bisa berupa gerakan mahasiswa. Ini juga bisa berupa komunitas religius independen, atau kelompok HAM.
- Efek Domino dari Daerah. Daerah dengan ketimpangan tinggi (Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT) dapat menjadi titik awal ledakan sosial yang menular ke pusat. → Efek: demonstrasi lokal bisa berkembang menjadi gerakan nasional dengan isu “keadilan daerah”.
Faktor Hukum dan HAM:
- Kriminalisasi Aktivis dan Jurnalis. Ketika hukum digunakan untuk membungkam kritik, masyarakat kehilangan saluran ekspresi legal. → Efek: perlawanan berubah bentuk menjadi underground movement — tidak lagi bisa diajak dialog.
- Erosi Keadilan Hukum di Publik. Ketika kasus besar seperti korupsi elite, pelanggaran HAM, dan penyalahgunaan kekuasaan tidak pernah tuntas, kepercayaan terhadap negara hukum runtuh. → Efek: hukum kehilangan legitimasi, dan rakyat mulai mencari “keadilan di luar hukum”.
- Pelemahan KPK dan Peradilan Independen. Hilangnya lembaga pengawasan efektif memperkuat persepsi bahwa hukum hanya milik penguasa. → Efek: muncul seruan reformasi hukum dan clean government movement seperti era Reformasi 1998.
Faktor Keamanan dan Militer: Overexposure Militer di Ranah Sipil. Ketika militer terlalu aktif dalam urusan sipil — dari proyek ekonomi hingga politik — potensi gesekan dengan masyarakat sipil meningkat. → Efek: kelelahan sosial terhadap “wajah keamanan di mana-mana”. Militerisasi Konflik Sosial. Jika protes sosial ditangani dengan pendekatan keamanan, bukan dialog, potensi eskalasi sangat tinggi. → Efek: muncul simbol-simbol perlawanan baru yang bisa mempersatukan gerakan lintas sektor (buruh, mahasiswa, petani, digital activists).
Krisis Kepercayaan Antar-Instansi Keamanan: Persaingan halus terjadi antara TNI dan Polri dalam mengelola keamanan politik dan ekonomi. Rivalry ini bisa menciptakan situasi berbahaya di lapangan. → Efek: instabilitas internal aparat, melemahkan kontrol negara.
Faktor Eksternal: Krisis Ekonomi Global atau Geopolitik Regional. Resesi global dapat menekan ekonomi Indonesia. Ketegangan di Laut Cina Selatan juga berpengaruh. Ketidakstabilan energi semakin memperburuk situasi. → Efek: tekanan eksternal menjadi katalis bagi krisis domestik.
Penutup
Jika kita menelaah secara analitik, Skenario Krisis Sosial dan Ledakan Politik muncul karena akumulasi tekanan sosial, ekonomi, hukum, dan politik.
Keterbatasan ruang aspirasi dan ketimpangan ekonomi memicu perlawanan rakyat. Kondisi ini juga menyebabkan demonstrasi besar atau gerakan sipil baru. Dinamika ini mirip dengan menjelang 1998. Namun, saat ini terjadi dalam konteks digital dan ekonomi modern.
Skenario krisis sosial-politik di Indonesia bukanlah akibat dari kekacauan, melainkan akibat dari stabilitas yang menutup ruang koreksi. Negara kuat tanpa legitimasi moral, hukum tanpa keadilan, dan pembangunan tanpa kesejahteraan — adalah formula yang pasti melahirkan gejolak.
“Setiap sistem yang menolak perubahan dari dalam, akan dipaksa berubah dari luar.”





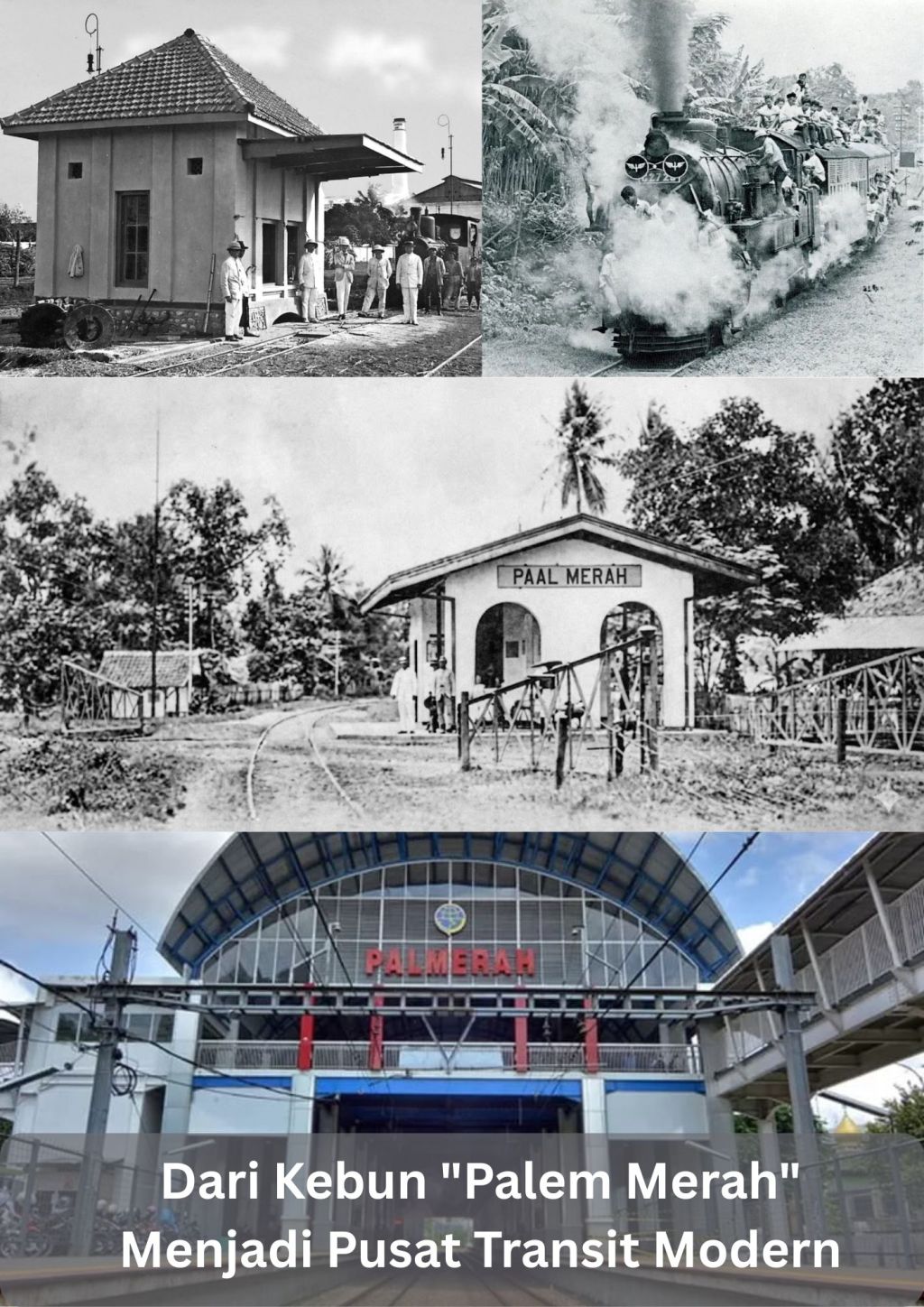
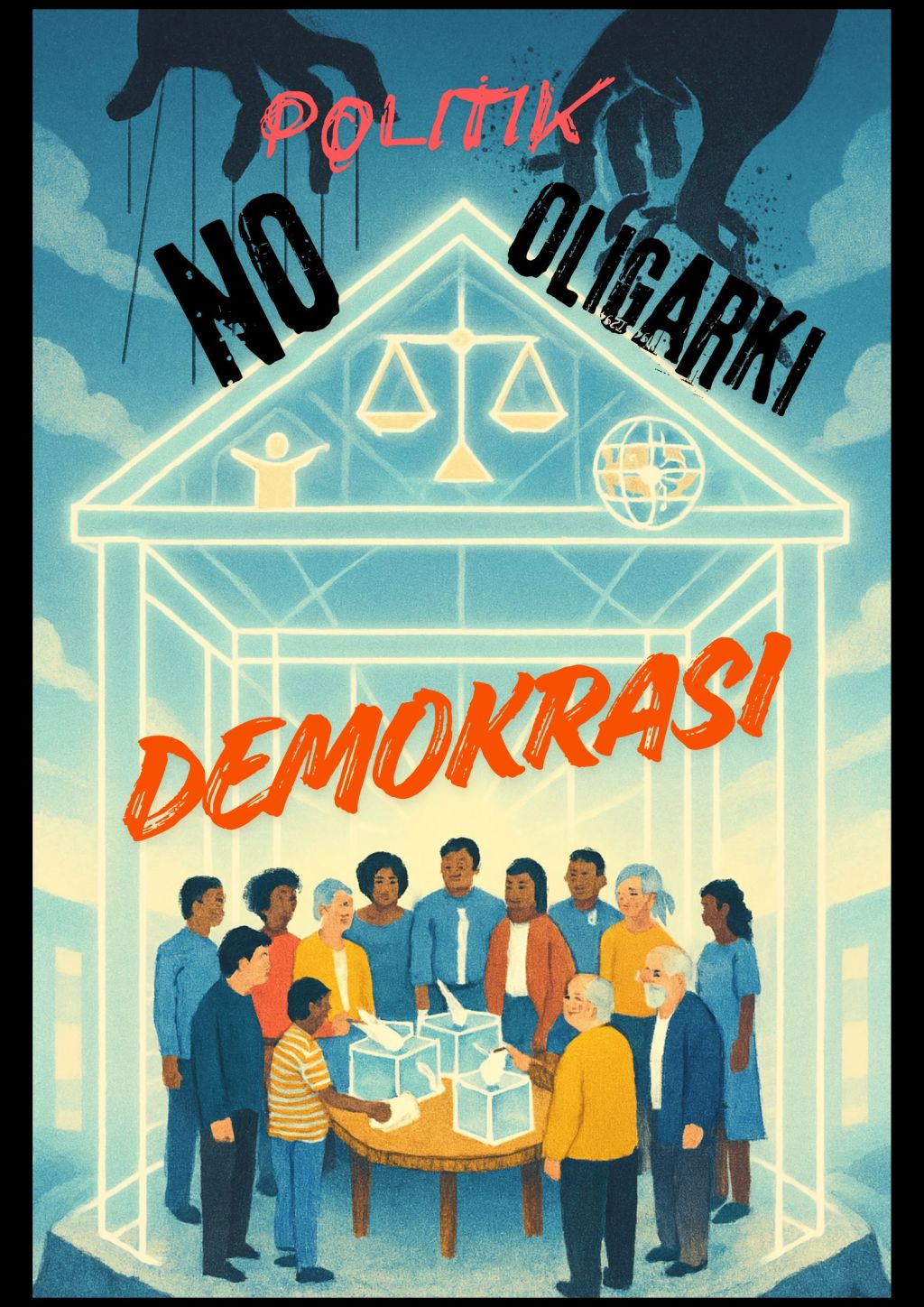




Leave a comment