Oeang Republik Indonesia
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak langsung diikuti mata uang sendiri. Awalnya, digunakan mata uang bersama: DJB, gulden Hindia Belanda, dan uang Jepang.
Pada 30 Oktober 1946, Pemerintah RI menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI), mata uang rupiah pertama, dicetak di Percetakan Canisius Yogyakarta. ORI hadir dalam 8 pecahan (1 sen hingga 100 rupiah).
Desainnya nasionalis seperti keris dan UUD 1945. Nilai 1 ORI setara dengan 50 gulden atau 0,5-gram emas.
Pasca-kemerdekaan, Indonesia tidak langsung memiliki mata uang tunggal. Antara 1945–1949, rupiah ORI bersaing dengan gulden Hindia Belanda. Uang Jepang juga menjadi pesaing. Bahkan ada mata uang lokal seperti ORIPS (Oeang Republik Indonesia Daerah Sumatera). Ini menciptakan kekacauan, karena nilai tukar antar-mata uang bervariasi di setiap wilayah.

ORI mengalami hiperinflasi karena perang dan blokade ekonomi Belanda, mencapai tingkat tidak terkendali. Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 mengakui kedaulatan Indonesia, membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada 27 Maret 1950, uang RIS diterbitkan oleh DJB, menggantikan ORI (1:1). Namun, RIS singkat; pada 17 Agustus 1950, NKRI kembali, dan rupiah RIS diganti rupiah NKRI.
Pada 1951, De Javasche Bank DJB di nasionalisasi menjadi Bank Indonesia (BI) melalui UU No. 11/1953, yang berlaku 1 Juli 1953. BI menerbitkan uang kertas Rp1–Rp100 pada 1952–1953, sementara pemerintah mengeluarkan pecahan kecil. Rupiah resmi ditetapkan sebagai mata uang tunggal pada 2 November 1949, dengan 1 rupiah = 100 sen. Bank Indonesia mulai menerbitkan uang rupiah kertas dengan seri tokoh dan kebudayaan Indonesia.
Sebelum rupiah diterapkan, Indonesia pernah menggunakan uang RIS (Republik Indonesia Serikat). Uang daerah (ORIDA) juga digunakan sebagai langkah pengendalian sirkulasi uang di berbagai daerah.
Beberapa daerah, seperti Aceh dan Sumatra Barat, mencetak uang kertas sendiri karena kurangnya pasokan ORI dari pusat. Misalnya, “Uang Serikat” di Sumatra digunakan hingga 1950. Fenomena ini menunjukkan desentralisasi ekonomi akibat perang kemerdekaan.
Orde Lama: Inflasi dan Devaluasi Awal
Era Orde Lama (1950–1966) ditandai ketidakstabilan. Inflasi meroket: 27% (1961), 174% (1962), hingga 600% (1965) membuat indeks harga 363 kali lebih tinggi dari 1958. Nilai tukar terhadap USD berubah dari Rp3,80 (1949) menjadi Rp31 (1956), Rp49 (1957), hingga Rp4.995 (1965).

Pada 1965, devaluasi besar terjadi, diikuti re-denominasi sementara dengan menghapus 3 nol (misalnya, Rp1.000 menjadi Rp 1 new rupiah) pada 1966, meski tidak permanen. Pecahan baru diperkenalkan, tapi hiperinflasi membuat sen usang. Periode ini mencerminkan konflik politik dan ekonomi pasca-kemerdekaan.
Pemerintah Orde Lama menghabiskan dana besar untuk proyek-proyek nasionalis. Contohnya, pembangunan monumen (Tugu Monas) dan proyek infrastruktur. Mereka juga melakukan kampanye militer seperti Konfrontasi dengan Malaysia (1963–1966) serta pembebasan Irian Barat (1961–1962). Pengeluaran ini tidak diimbangi oleh pendapatan negara yang memadai.
Untuk menutup defisit anggaran, pemerintah mencetak uang secara masif melalui Bank Indonesia. Hal ini meningkatkan jumlah uang yang beredar (money supply), yang memicu inflasi. Pada 1965, jumlah uang beredar melonjak drastis, memperburuk hiperinflasi.
| Tahun | Defisit Anggaran (% dari Penerimaan) | Keterangan |
|---|---|---|
| 1961 | 29,7% | Awal kenaikan defisit akibat nasionalisasi aset asing. |
| 1962 | 38,7% | Dampak Operasi Trikora (pembebasan Irian Barat). |
| 1963 | 50,8% | Eskalasi Konfrontasi dengan Malaysia. |
| 1964 | 58,4% | Inflasi mulai meroket, pengeluaran militer mendominasi. |
| 1965 | 63,4% | Puncak defisit, diikuti hiperinflasi 600%. |
Soekarno menggunakan rupiah sebagai alat propaganda. Uang kertas era 1950-an hingga 1960-an sering menampilkan gambar proyek nasionalis, seperti Monumen Nasional (Monas). Ada juga motif budaya lokal. Keduanya bertujuan membangun kebanggaan nasional di tengah ketidakstabilan ekonomi. Pecahan Rp 1 (1951) menampilkan petani dan sawah, mencerminkan visi Soekarno tentang Indonesia sebagai negara agraris yang swasembada.
Pada 25 Agustus 1959, pemerintah melakukan “sanering” (pemotongan nilai uang) untuk mengendalikan inflasi. Uang kertas Rp500 dan Rp1.000 dipotong nilainya menjadi 10% (misalnya, Rp1.000 menjadi Rp100), dan nilai tukar resmi terhadap USD diubah dari Rp11,40 ke Rp45. Kebijakan ini gagal karena tidak diimbangi pengendalian anggaran, malah memicu kepanikan dan penimbunan.
Menjelang akhir Orde Lama, pemerintah mencoba redenominasi dengan menghapus tiga nol (Rp1.000 menjadi Rp1 “new rupiah”). Namun, ini tidak efektif karena hiperinflasi terus berlanjut, dan kebijakan ini dicabut di era Orde Baru.
Konfrontasi Malaysia (1963–1966): Kampanye militer ini menghabiskan devisa dan anggaran besar, diperkirakan 20–30% dari APBN, yang dibiayai melalui pencetakan rupiah. Ini mempercepat pelemahan nilai tukar dari Rp49 (1957) ke Rp4.995 (1965).
Soekarno mengalokasikan dana untuk proyek prestise. Proyek ini meliputi Monas, Gelora Bung Karno, dan Hotel Indonesia. Keseluruhan proyek memakan biaya milliaran rupiah. Misalnya, pembangunan Monas (1961–1965) menelan biaya setara US$7 juta (sekitar Rp35 miliar saat itu), sebagian dibiayai pinjaman dari Uni Soviet. Proyek ini memicu kritik karena dianggap boros di tengah krisis ekonomi.
Hiperinflasi membuat harga barang pokok seperti beras melonjak. Pada 1965, harga beras bisa naik 10 kali lipat dalam hitungan bulan. Kenaikan ini memaksa banyak keluarga beralih ke barter atau menanam ubi sebagai pengganti beras. Fenomena ini dikenal sebagai “ekonomi jagung” di beberapa daerah.
Karena pencetakan berlebih, kualitas uang kertas menurun. Banyak uang kertas sobek atau lusuh, dan pecahan kecil (sen) menjadi tidak relevan akibat inflasi, membuat transaksi sehari-hari sulit.
Rupiah di era Orde Lama bukan hanya alat ekonomi. Itu juga merupakan cerminan ambisi Soekarno untuk membangun identitas nasional. Meski sering kali dengan biaya ekonomi yang besar. Dari desain patriotik hingga kegagalan sanering, rupiah menjadi saksi perjuangan Indonesia menegaskan diri di tengah tekanan internal dan eksternal.
Orde Baru

Era Orde Baru (1966–1998) di bawah Presiden Soeharto adalah periode penting bagi rupiah. Periode ini ditandai dengan upaya stabilisasi ekonomi setelah hiperinflasi Orde Lama. Masa itu juga mencatat pertumbuhan pesat dan tantangan besar seperti Krisis Moneter Asia 1997–1998. Rupiah tidak hanya menjadi alat tukar, tetapi juga cerminan kebijakan ekonomi, politik otoriter, dan dinamika sosial Indonesia.
Setelah krisis ekonomi Orde Lama, Soeharto menerapkan kebijakan “anggaran berimbang” pada 1967, menghentikan pencetakan uang berlebih untuk menutup defisit. Ini berhasil menurunkan inflasi dari 600% (1965) menjadi 10% pada 1969.
UU No. 13/1968 memperkuat peran BI sebagai satu-satunya penerbit rupiah, menghapus kebijakan Orde Lama yang memungkinkan pemerintah mencetak uang. Ini meningkatkan disiplin moneter.
Rupiah didevaluasi secara bertahap untuk menyesuaikan nilai tukar dengan kondisi ekonomi. Contohnya, dari Rp4.995/USD (1965) menjadi Rp378/USD (1970), Rp415/USD (1971), dan Rp625/USD (1978). Kebijakan ini didukung oleh cadangan devisa dari ekspor minyak dan bantuan asing.
Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), dipimpin Belanda dan AS, memberikan pinjaman dan hibah US$1,03 miliar (1966–1972) untuk stabilisasi rupiah. Ini membantu membayar utang Orde Lama (US$2,7 miliar) dan memperkuat kepercayaan terhadap rupiah.
Untuk memenuhi kebutuhan uang kertas berkualitas tinggi, Indonesia menggandeng percetakan asing seperti Thomas De La Rue (Inggris) pada 1970-an, menunjukkan modernisasi infrastruktur monete
Uang kertas Orde Baru mencerminkan agenda “Pembangunan Nasional”. Pecahan Rp1.000–Rp10.000 (1970-an) menampilkan gambar infrastruktur seperti bendungan, jembatan, dan pelabuhan. Ini juga menampilkan tokoh nasional seperti Diponegoro dan Imam Bonjol. Gambar-gambar ini dipilih untuk mempromosikan kemajuan dan persatuan.
Pertumbuhan ekonomi mendorong penerbitan pecahan besar, seperti Rp10.000 dan Rp50.000. Ini menunjukkan meningkatnya transaksi ekonomi, meski inflasi tetap menjadi tantangan.
Hingga 1971, rupiah dipatok ke dolar AS berdasarkan sistem Bretton Woods. Setelah runtuhnya sistem ini, Indonesia beralih ke nilai tukar mengambang terkendali pada 1978. Bank Indonesia (BI) mengintervensi pasar untuk menjaga stabilitas. Nilai tukar relatif stabil di Rp2.000/USD selama 1980-an hingga awal 1990-an.
Devaluasi dilakukan untuk mendukung ekspor non-migas, seperti pada 1983 (Rp970/USD) dan 1986 (Rp1.664/USD). Ini meningkatkan daya saing ekspor tekstil dan kayu, meski memicu inflasi impor.
Kenaikan harga minyak dunia pada 1973–1974 dan 1979–1980 meningkatkan pendapatan ekspor Indonesia. Pada 1974, ekspor minyak menyumbang 70% devisa, memperkuat cadangan untuk stabilisasi rupiah. Ini memungkinkan BI menjaga nilai tukar di Rp415/USD selama dekade 1970-an.
Pada 1980-an, pemerintah mendorong ekspor non-migas (tekstil, kayu lapis, karet) untuk mengurangi ketergantungan pada minyak. Keberhasilan ini menjaga rupiah stabil hingga awal 1990-an, meski kerentanan terhadap fluktuasi global tetap ada.
Pertumbuhan ekonomi 6–7% per tahun pada 1980-an hingga awal 1990-an menciptakan kelas menengah yang meningkatkan permintaan barang konsumsi. Rupiah menjadi simbol daya beli baru, terlihat dari maraknya mal dan produk impor.
Rupiah juga terkait dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Proyek-proyek besar sering dibiayai pinjaman dalam rupiah atau dolar. Namun, banyak yang dikorupsi oleh kroni Soeharto. Hal ini melemahkan kepercayaan terhadap ekonomi jangka panjang.
Pecahan koin kecil (Rp1–Rp50) mulai usang pada 1980-an karena inflasi, digantikan kertas untuk pecahan rendah. Ini mencerminkan perubahan nilai rupiah dalam kehidupan sehari-hari.
Nominal Rp50.000 adalah salah satu pecahan uang kertas rupiah yang paling sering digunakan dalam transaksi sehari-hari di Indonesia. Ini terutama digunakan untuk pembayaran besar seperti belanja bulanan atau transportasi.
Pecahan ini pertama kali diterbitkan pada 1993. Saat itu adalah era Orde Baru yang penuh pertumbuhan ekonomi. Desainnya telah mengalami evolusi berkali-kali untuk mencerminkan perubahan politik, budaya, dan teknologi keamanan.
Uang kertas ini diterbitkan sebagai uang peringatan “25 Tahun Pembangunan” di era Presiden Soeharto (1968-1993). Bagian depan menampilkan potret Soeharto. Ia dikenal sebagai “Soeharto Mesem” karena senyumannya yang ikonik. Ini adalah karya engraver Peruri bernama Mujirun. Sementara itu, bagian belakang menggambarkan Bandara Soekarno-Hatta dengan pesawat lepas landas. Ini adalah simbol kemajuan infrastruktur dan globalisasi Indonesia saat itu. Warna dominan ungu mencerminkan seri “Pembangunan”.
Ini adalah satu-satunya pecahan rupiah yang pernah menampilkan presiden yang masih berkuasa, menjadikannya simbol propaganda Orde Baru. Total dicetak jutaan lembar, tapi desain ini kontroversial karena dianggap memuja kepemimpinan Soeharto.
Krisis 1997–1998 mengungkap kelemahan ekonomi Orde Baru, seperti ketergantungan pada utang swasta, korupsi, dan kurangnya reformasi perbankan. Rupiah menjadi korban utama, tetapi juga pemicu reformasi moneter di era Reformasi.
Krisis dipicu oleh spekulasi terhadap baht Thailand, yang menyebar ke Indonesia. Utang swasta jangka pendek (US$34 miliar pada 1997), korupsi, dan kelemahan sektor perbankan memperburuk kepercayaan investor. Rupiah jatuh ke level terendah Rp16.650/USD pada Juni 1998.
Inflasi 80% membuat harga beras dan bahan pokok melonjak, memicu kerusuhan Mei 1998 yang mengguncang Jakarta dan kota besar lainnya. Krisis ini menjadi pemicu jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998.
Reformasi
Pasca-Soeharto, rupiah perlahan pulih melalui reformasi BI dan penguatan dengan regulasi UU No. 7/2011 tentang Mata Uang menegaskan rupiah sebagai simbol kedaulatan.
| Tahun Emisi | Presiden / Era | Fokus Desain | Ciri Utama |
|---|---|---|---|
| 1998–1999 | BJ Habibie / Awal Reformasi | Stabilitas pasca-krisis | Desain klasik, fokus simbol nasional |
| 2004–2009 | Megawati – SBY | Modernisasi moneter | Warna cerah, fitur keamanan meningkat |
| 2016 | Joko Widodo | NKRI & keragaman budaya | 11 Pahlawan Nasional, desain tematik |
| 2022 | Joko Widodo | Penyempurnaan visual & keamanan | Warna dinamis, fitur modern, bentuk proporsional |
| Nilai Nominal | Gambar Pahlawan Nasional (Depan) | Gambar Belakang (Ikon Budaya/Nature) |
|---|---|---|
| Rp1.000 | Tjut Meutia | Tari Tifa, Banda Neira, Bunga Anggrek Larat |
| Rp2.000 | Mohammad Husni Thamrin | Tari Serimpi, Ngarai Sianok, Bunga Jeumpa |
| Rp5.000 | Dr. K.H. Idham Chalid | Tari Gambyong, Gunung Bromo, Bunga Sedap Malam |
| Rp10.000 | Frans Kaisiepo | Tari Pakarena, Taman Nasional Wakatobi, Bunga Cempaka Hutan Kasar |
| Rp20.000 | Dr. G.S.S.J. Ratulangi | Tari Gong, Derawan, Bunga Anggrek Hitam |
| Rp50.000 | Ir. H. Djuanda Kartawidjaja | Tari Legong, Pantai Pink Lombok, Bunga Jepun |
| Rp100.000 | Soekarno & Mohammad Hatta | Tari Topeng Betawi, Raja Ampat, Bunga Anggrek Bulan |
Pada 2000, rupiah stabil di kisaran Rp8.000–Rp10.000/USD. BI menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas (free floating) sejak 1997, dengan intervensi terbatas untuk mencegah volatilitas ekstrem. Pada 2005, inflasi turun ke 10,5%, dan pada 2010 menjadi 5,1%, menunjukkan pemulihan ekonomi.
Krisis memaksa BI mencetak pecahan besar seperti Rp100.000 polimer (1999) untuk mengakomodasi inflasi. Namun, pemulihan rupiah di awal Reformasi menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia, didukung ekspor komoditas seperti batubara dan minyak sawit.
BI meluncurkan desain baru untuk menghapus simbol Orde Baru (misalnya, potret Soeharto pada Rp50.000 1993). Uang kertas menampilkan pahlawan nasional seperti Cut Nyak Dhien (Rp10.000), I Gusti Ngurah Rai (Rp50.000), dan Otto Iskandardinata (Rp20.000), dengan sisi belakang menonjolkan budaya dan alam Indonesia, seperti Tari Saman atau Danau Beratan.
Seri 2016 adalah yang pertama menggunakan teknologi keamanan canggih seperti watermark 3D dan tinta berubah warna. Sementara seri 2022 dirancang lebih kecil. Rp50.000 berukuran 140×71 mm untuk aksesibilitas dan dilapisi anti-kotor untuk daya tahan. Desain ini juga melibatkan kertas impor dari Swiss.
Untuk memperingati 75 tahun Kemerdekaan RI, BI menerbitkan Rp75.000 dengan gambar Soekarno dan Mohammad Hatta di depan, serta satelit dan anak-anak berpakaian adat di belakang. Ini adalah pecahan komemoratif pertama sejak Rp50.000 “25 Tahun Pembangunan” (1993). Hanya 75 juta lembar dicetak, menjadikannya barang koleksi.
BI meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada 2019 untuk menyatukan pembayaran digital di Indonesia. Ini memungkinkan transaksi rupiah via ponsel, mengurangi ketergantungan pada uang fisik. Pada 2023, QRIS digunakan oleh 26 juta merchant, dengan transaksi tahunan Rp1.200 triliun.
Pada 2025, transaksi non-tunai (termasuk QRIS dan kartu) menyumbang 60% dari total transaksi ritel, menunjukkan pergeseran besar dari uang kertas. Namun, rupiah fisik tetap dominan di daerah pedesaan, mencerminkan dualisme ekonomi Indonesia.
Rupiah menghadapi tekanan global seperti pandemi COVID-19 (2020) dan perang dagang. Pada November 2025, nilai tukar Rp16.685/USD, melemah 7,2% dari tahun sebelumnya. Inflasi stabil di 2,86% (Oktober 2025), tetapi tekanan dari kenaikan harga energi dan impor tetap menjadi tantangan.
Pada 2020, rupiah sempat melemah ke Rp17.000/USD akibat pandemi, tetapi pulih lebih cepat dibandingkan mata uang lain di ASEAN, menunjukkan ketahanan moneter era Reformasi.
BI sedang mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC) berbasis blockchain, direncanakan uji coba pada 2025–2026. Rupiah Digital bertujuan meningkatkan efisiensi transaksi lintas batas dan inklusi keuangan, terutama di daerah terpencil. Proyek ini menarik perhatian global karena Indonesia adalah salah satu pelopor CBDC di ASEAN.
Usulan Redenominasi (2010–2014): BI mengusulkan menghapus tiga nol dari rupiah (misalnya, Rp50.000 menjadi Rp50) untuk menyederhanakan transaksi dan meningkatkan persepsi nilai rupiah. Rencana ini disetujui DPR pada 2010. Namun, rencana tersebut ditunda pada 2014. Hal ini karena kondisi ekonomi global yang tidak mendukung. Ada juga kekhawatiran akan kebingungan publik.
Pada 2023, wacana redenominasi muncul kembali, dengan BI menargetkan implementasi pada 2030 jika stabilitas ekonomi terjaga. Simulasi BI menunjukkan redenominasi bisa menghemat biaya pencetakan dan meningkatkan efisiensi akuntansi, tetapi tantangan edukasi publik tetap besar.
| Fase | Durasi | Tujuan Utama |
|---|---|---|
| Tahap I – Persiapan | 2 tahun | Sosialisasi, penyesuaian sistem, penyusunan peraturan |
| Tahap II – Transisi (Dual Currency/Price) | 3 tahun | Penggunaan uang lama dan baru secara bersamaan |
| Tahap III – Implementasi penuh | 2 tahun | Uang lama ditarik, hanya uang baru berlaku |
Rupiah di era Reformasi mencerminkan perjalanan Indonesia dari krisis ke demokrasi. Rupiah juga menunjukkan transisi dari uang kertas tradisional ke digitalisasi. Selain itu, ada perjalanan dari tantangan global ke ketahanan lokal. Pecahan komemoratif, desain inklusif, dan rencana Rupiah Digital menunjukkan adaptasi rupiah terhadap zaman. Tantangan seperti pelemahan nilai tukar mengingatkan pada kerentanan ekonomi.

Kesimpulan
Secara keseluruhan, evolusi rupiah adalah kisah ketahanan dan adaptasi. Dari ORI yang lahir di tengah perang, rupiah mencerminkan perjuangan Indonesia melawan krisis. Rupiah juga membangun identitas, dan merangkul masa depan di era global. Meski tantangan seperti inflasi dan pelemahan nilai tukar terus ada, BI terus memperkuat rupiah melalui reformasi moneter dan edukasi publik. Rupiah bukan hanya mata uang, tetapi narasi bangsa yang terus berkembang, menginspirasi kebanggaan dan optimisme untuk masa depan.
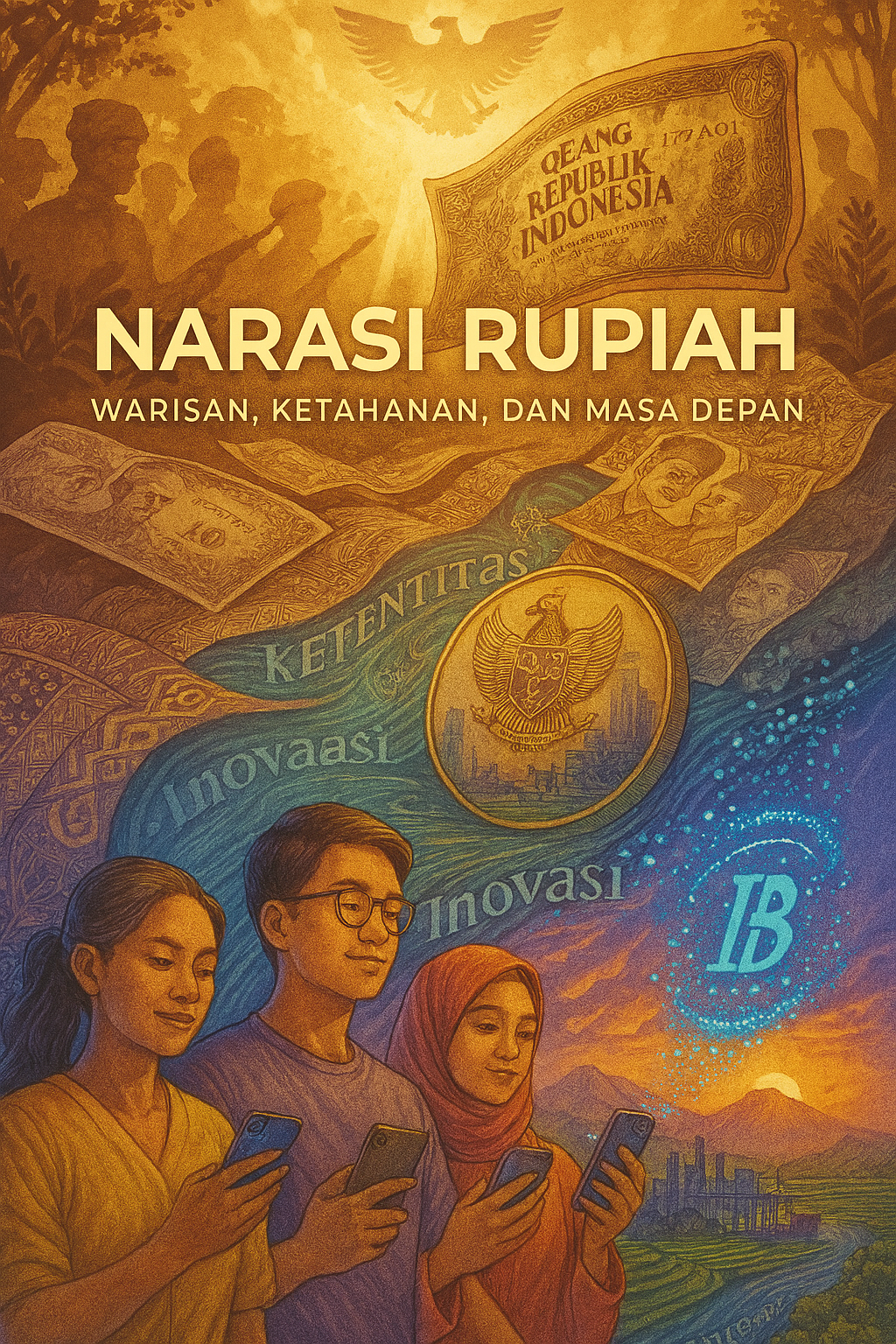




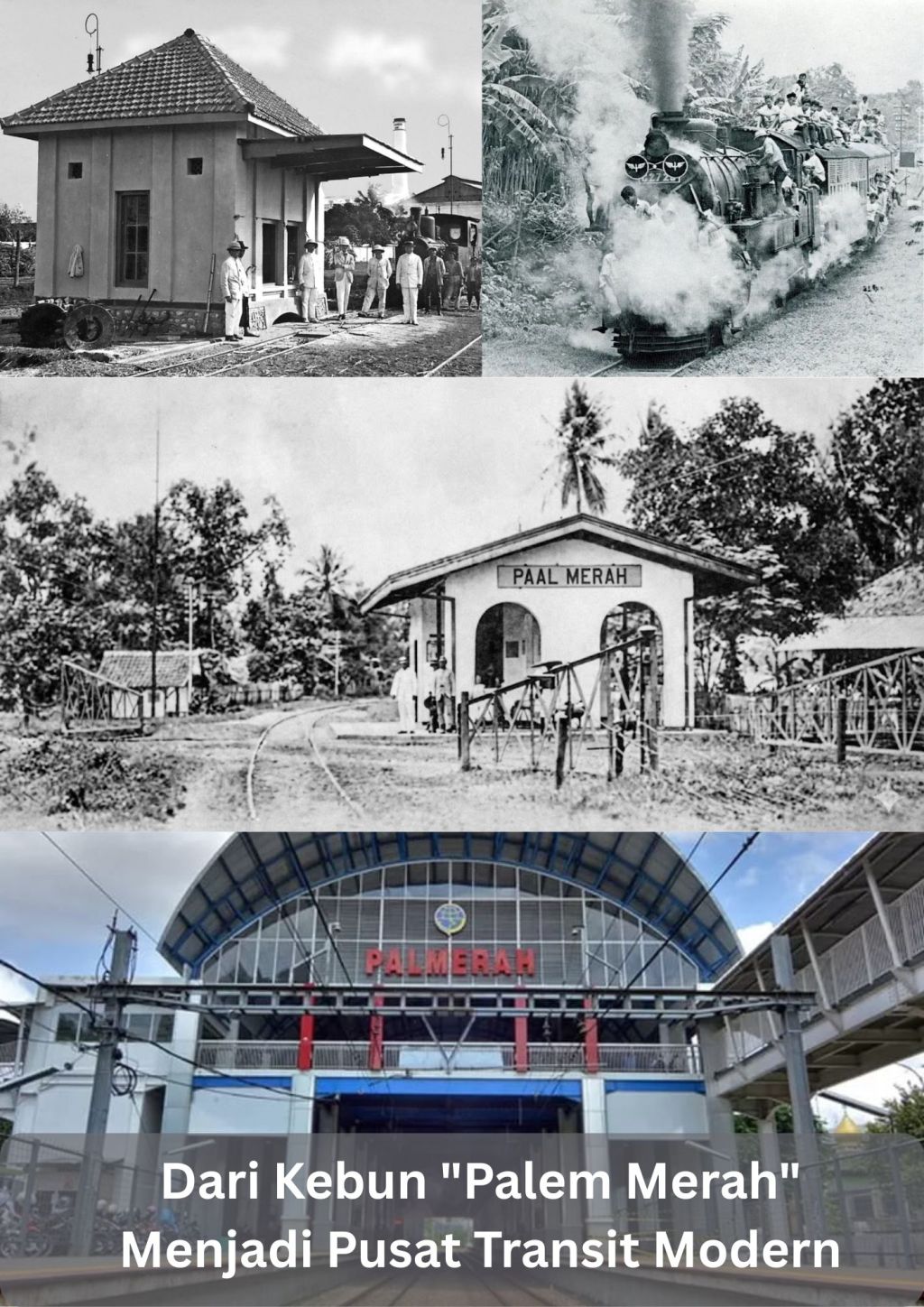
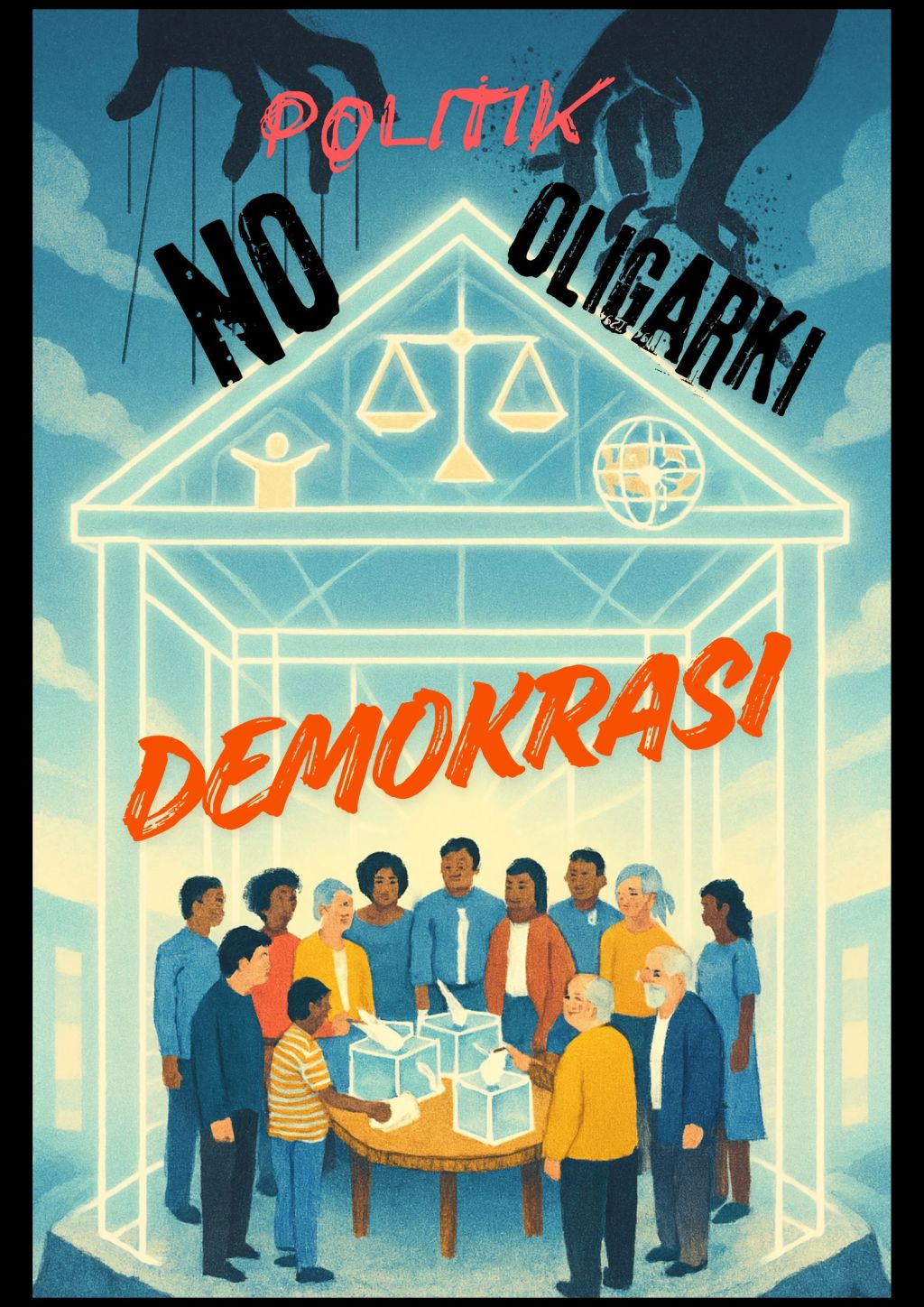




Leave a comment