Catatan Kritis atas Arah Penuntutan Tipikor di Indonesia
Korupsi pengadaan barang dan jasa sejak lama dipahami sebagai jantung korupsi anggaran di Indonesia. Di sanalah uang publik bertemu dengan kekuasaan diskresioner. Di tempat itu pula, praktik markup—penggelembungan harga yang disengaja—menjadi mekanisme paling lazim. Itu adalah cara untuk mengubah uang negara menjadi keuntungan privat. Namun dalam beberapa tahun terakhir, muncul kecenderungan yang patut dikritisi secara serius. Korupsi pengadaan dituntut tanpa penjelasan tegas tentang praktik markup itu sendiri. Narasi panjang tentang “kerugian negara” menggantikan penjelasan tersebut.
Pertanyaannya mendasar: Apakah korupsi pengadaan masih dipahami sebagai kejahatan ekonomi berbasis rekayasa harga? Atau, apakah kini telah direduksi menjadi sekadar kegagalan kebijakan yang dipidana?
Markup: Mekanisme, Bukan Sekadar Istilah
Dalam logika hukum pidana pengadaan, markup bukan jargon teknis, melainkan mekanisme kejahatan (actus reus). Negara tidak pernah berbicara soal laba; negara hanya membayar harga. Maka satu-satunya cara uang negara dapat “dicuri” melalui pengadaan adalah dengan menciptakan selisih harga yang tidak sah. Selisih itulah yang kemudian dapat mengalir sebagai kickback, komisi terselubung, atau keuntungan tidak langsung.
Tanpa markup, tidak ada surplus ilegal. Tanpa surplus ilegal, unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” menjadi problematis. Di titik ini, perbedaan antara kerugian negara dan korupsi menjadi krusial. Tidak setiap kerugian negara adalah korupsi. Sebagian besar kerugian justru lahir dari kebijakan yang keliru. Kerugian juga bisa berasal dari asumsi ekonomi yang salah. Kegagalan desain program juga menyumbang kerugian.
Hukum pidana tidak diciptakan untuk menghukum kebijakan yang gagal, melainkan perbuatan jahat yang disengaja.
Dakwaan Minimalis dan Krisis Konstruksi Hukum
Secara formil, KUHAP memang tidak melarang dakwaan minimalis. Pasal 143 hanya mensyaratkan dakwaan disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Namun problemnya bukan soal kelengkapan administratif, melainkan kualitas konstruksi delik.
Dakwaan yang panjang tetapi tidak menjelaskan:
- di mana praktik markup terjadi,
- bagaimana harga “dibentuk secara melawan hukum”,
- dan dari mana asal uang yang disebut “memperkaya”,
adalah dakwaan yang secara pidana miskin mekanisme. Ia sah secara prosedural, tetapi rapuh secara substansial. Dalam standar akademik hukum pidana, model dakwaan seperti ini lebih menyerupai laporan audit administratif daripada instrumen penuntutan kejahatan ekonomi.
Di sinilah kritik menjadi relevan: ketika penuntutan korupsi pengadaan dimulai dari kerugian negara. Ini digunakan sebagai titik awal, bukan sebagai akibat dari kejahatan. Maka, logika pidana dibalik. Negara diposisikan sebagai korban terlebih dahulu, lalu kejahatan dicari belakangan. Pendekatan ini berbahaya bagi prinsip kepastian hukum.
Audit Forensik dan Money Trail sebagai “Alat Bukti Mahkota”
Dalam praktik terbaik (best practice) penegakan hukum tipikor, terdapat urutan pembuktian yang relatif mapan:
- Audit forensik membuktikan adanya praktik markup—rekayasa harga yang disengaja dan tidak dapat dijustifikasi secara ekonomi.
- Money trail menunjukkan ke mana selisih hasil markup itu mengalir, baik langsung maupun melalui pihak terafiliasi.
- Barulah unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” hidup secara yuridis.
Audit kerugian negara tanpa audit forensik markup hanyalah pengukuran akibat, bukan pembuktian kejahatan. Money trail tanpa titik penciptaan surplus ilegal hanyalah asumsi aliran dana, bukan bukti korupsi.
Jika dua pilar ini tidak berdiri tegak, maka perkara korupsi pengadaan kehilangan jantungnya.
Antara Efisiensi Penuntutan dan Keadilan Substantif
Sering kali pembelaan terhadap dakwaan minimalis adalah alasan pragmatis: perkara besar, kompleks, dan menyangkut kebijakan nasional. Jaksa memilih jalur “aman” secara formil agar perkara masuk pembuktian. Namun pragmatisme semacam ini mengandung risiko sistemik.
Pertama, kriminalisasi kebijakan. Pengambil keputusan menjadi rentan dipidana bukan karena kejahatan, melainkan karena hasil kebijakan yang dinilai merugikan setelah fakta. Ini menciptakan efek jera yang salah sasaran dan melumpuhkan keberanian administrasi publik.
Kedua, erosinya legitimasi pengadilan tipikor. Jika publik melihat bahwa korupsi dihukum tanpa kejelasan mekanisme kejahatan, pengadilan tidak lagi dipandang sebagai arena keadilan. Sebaliknya, itu dipandang sebagai instrumen kekuasaan.
Ketiga, ketidakadilan sosial. Ironisnya, dakwaan yang lemah berpotensi membebaskan pelaku korupsi sejati di tingkat akhir. Hal ini meninggalkan preseden buruk bagi penegakan hukum ke depan.
Masa Depan Pengadilan Korupsi Pengadaan
Jika tujuan akhir pemberantasan korupsi adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka arah pengadilan tipikor harus diperjelas.
Pertama, kembali ke inti korupsi pengadaan: markup. Setiap dakwaan harus menjawab secara eksplisit: berapa harga wajar, bagaimana harga digelembungkan, dan mengapa selisih itu ilegal.
Kedua, menempatkan audit forensik sebagai fondasi, bukan pelengkap. Audit kerugian negara penting, tetapi tidak cukup. Tanpa forensik ekonomi, hukum pidana kehilangan presisinya.
Ketiga, memperketat standar pembuktian “memperkaya diri”. Uang tidak boleh diasumsikan “mengalir” hanya karena negara rugi. Ia harus ditunjukkan, ditelusuri, dan dikaitkan secara kausal.
Keempat, memisahkan secara tegas kesalahan kebijakan dari kejahatan. Ini bukan melemahkan pemberantasan korupsi, melainkan justru memperkuatnya agar tidak salah sasaran.
Penutup
Korupsi pengadaan bukan soal angka besar atau narasi kerugian yang panjang. Ia adalah kejahatan ekonomi yang konkret, terukur, dan bermekanisme. Ketika praktik markup dihilangkan dari pusat analisis, hukum pidana kehilangan kompasnya.
Masa depan pengadilan tipikor ditentukan oleh satu pilihan mendasar: apakah kita ingin menghukum akibat, atau membongkar kejahatan. Hanya dengan memilih yang kedua, pengadilan dapat menjadi instrumen keadilan sosial. Pengadilan bukan sekadar panggung penjatuhan vonis. Pengadilan adalah penjaga rasionalitas hukum dalam negara hukum yang dewasa.





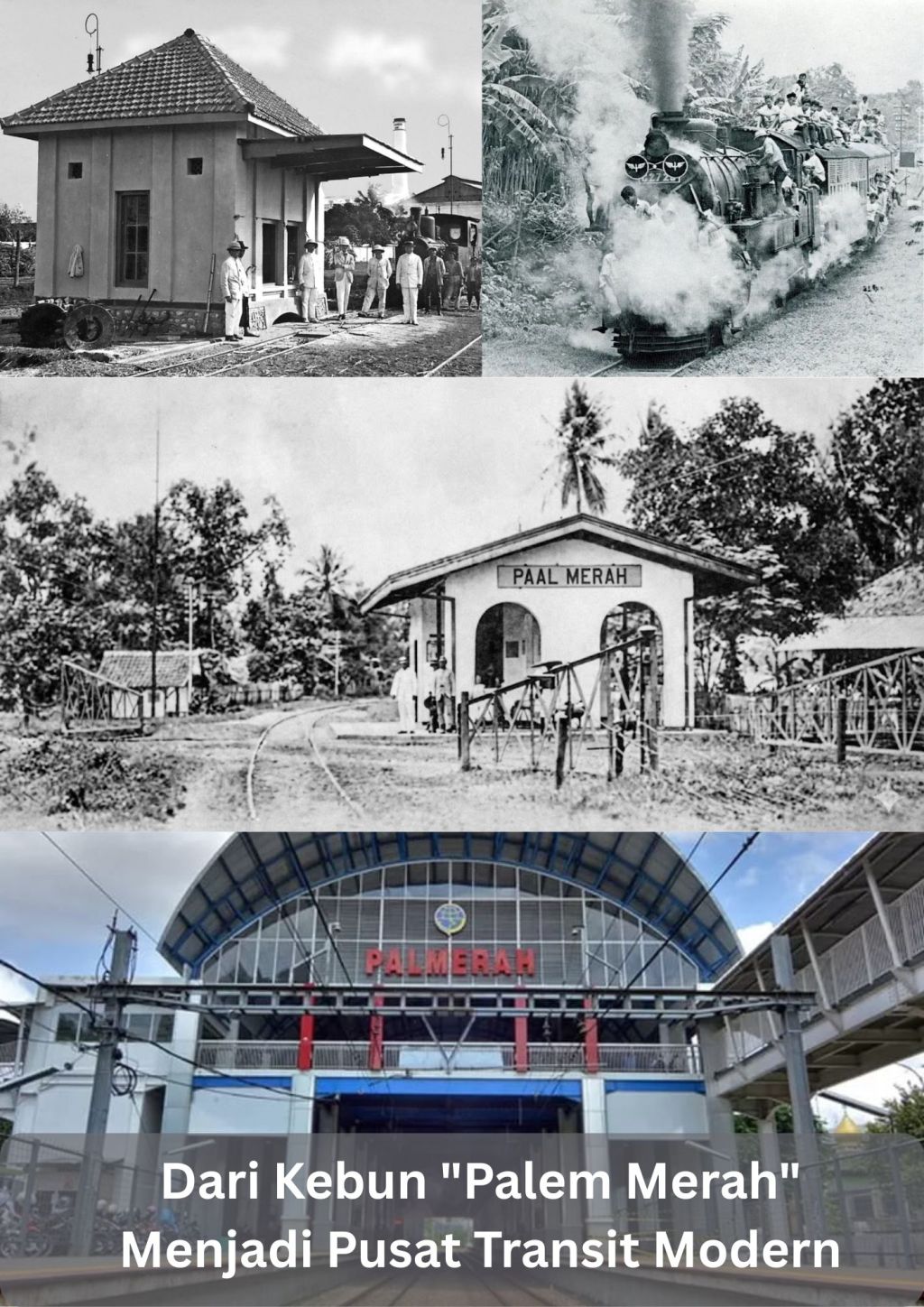
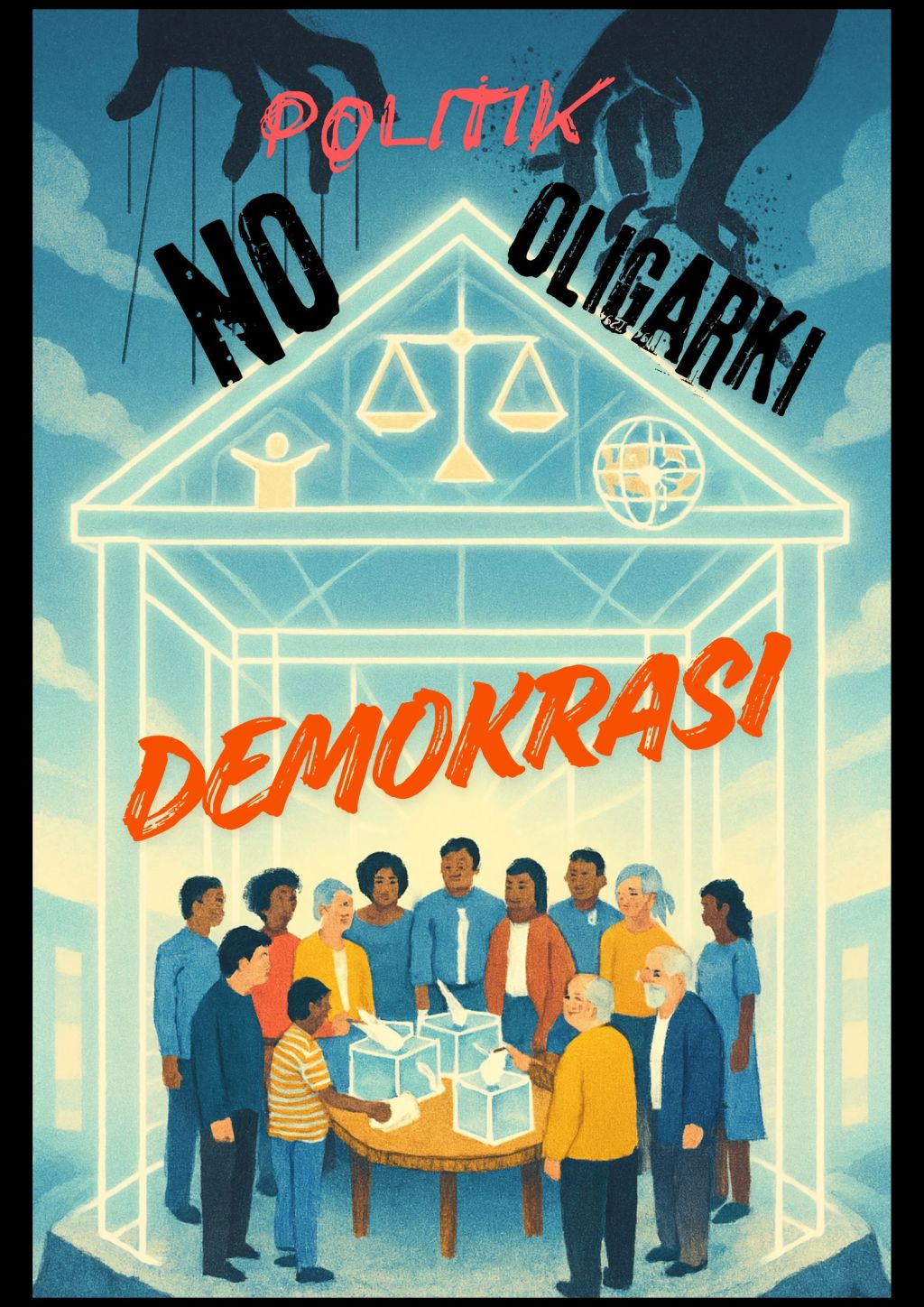




Leave a comment