
Analisis Sosiologi Politik terhadap Keterjebakan dalam Oligarki Orde Baru dan Stagnasi Pembangunan Bona Pasogit
Fenomena sosiopolitik di Sumatera Utara menyajikan sebuah teka-teki yang kompleks. Ini terutama berkaitan dengan peran elite etnis Batak dalam struktur kekuasaan nasional. Fenomena ini membingungkan para akademisi dan praktisi pembangunan.
Di satu sisi, etnis Batak dikenal secara luas memiliki etos kerja yang tangguh. Mereka juga dikenal memiliki kecerdasan intelektual yang tajam. Secara teoritis, filosofi hidup 3H (Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon) mampu menjadi katalisator. Ini dapat mendorong kemajuan luar biasa bagi daerah asal mereka, yang dikenal sebagai Bona Pasogit.
Namun, realitas empiris menunjukkan sebuah diskoneksi yang mengkhawatirkan. Banyak figur Batak menempati posisi puncak dalam hierarki politik, militer, dan bisnis di Jakarta. Daerah-daerah di kawasan Tapanuli dan sekitarnya sering kali tetap terjebak dalam kemiskinan sistemik. Mereka juga mengalami kerusakan ekosistem yang masif dan konflik agraria yang berkepanjangan.
Keterjebakan ini bukan merupakan sebuah kebetulan sejarah, melainkan produk dari evolusi sistemik yang berakar pada struktur oligarki warisan Orde Baru. Sistem ini telah berhasil mengooptasi potensi elite lokal melalui mekanisme patronase yang sentralistik. Loyalitas kepada pusat kekuasaan di Jakarta jauh lebih bernilai secara politik dan ekonomi. Hal ini lebih diutamakan dibandingkan komitmen pada pembangunan daerah asal.
Dalam ekosistem yang predatoris ini, elite Batak sering kali dipaksa. Mereka juga dapat secara sukarela memilih untuk menjadi bagian dari “logika ekstraktif.” Pandangan ini melihat tanah leluhur mereka bukan sebagai ruang hidup yang suci. Sebaliknya, tanah tersebut dianggap sebagai komoditas yang harus dikeruk demi akumulasi modal global.
Genealogi Elite Batak dalam Struktur Kekuasaan Orde Baru
Untuk memahami mengapa elite Batak cenderung terjebak dalam sistem oligarki, analisis harus dimulai dari cara Orde Baru membangun fondasi kekuasaannya. Rezim Soeharto menciptakan sistem politik yang sangat terpusat dengan Golkar sebagai instrumen utama kontrol sosial dan politik.
Dalam sistem ini, rekrutmen elite dilakukan melalui jalur birokrasi dan militer yang sangat ketat. Mobilitas vertikal hanya dimungkinkan bagi mereka yang bersedia menjadi klien dari patron pusat.
Banyak putra terbaik Batak menempati posisi strategis di militer. Beberapa di antaranya adalah di Kopassus dan birokrasi. Mereka akhirnya terintegrasi ke dalam jaring laba-laba patronase ini.
Loyalitas primordial yang kuat ada dalam masyarakat Batak. Secara tradisional, masyarakat ini diikat oleh sistem marga. Negara justru memanfaatkan loyalitas ini sebagai alat pengelompokan yang mudah dikendalikan.
Orde Baru membungkus ikatan primordial ini dalam organisasi-organisasi yang berada di bawah pengawasan ketat. Ini membuat potensi kritis dari kearifan lokal menjadi tumpul. Substansi nilai-nilai leluhur sering kali diabaikan untuk menjaga stabilitas politik nasional.
Elite yang muncul dari sistem ini adalah mereka yang mahir melakukan negosiasi di ruang-ruang kekuasaan Jakarta. Namun, mereka sering kali kehilangan sentuhan dengan realitas akar rumput di huta masing-masing.
Peran Militer dan Transformasi ke Dunia Bisnis
Keterlibatan signifikan perwira militer berdarah Batak dalam struktur Orde Baru memberikan dampak jangka panjang terhadap pola kepemimpinan mereka. Tokoh-tokoh seperti Luhut Binsar Pandjaitan, T.B. Silalahi, Feisal Tanjung, dan Maraden Panggabean bukan hanya figur militer, melainkan juga pemain kunci dalam transisi ekonomi politik Indonesia.
Transformasi dari prajurit lapangan menjadi pengusaha dan politisi “segala urusan” merupakan contoh. Ini mencerminkan bagaimana modal sosial militer dikonversi menjadi modal finansial. Selain itu, juga menjadi modal politik di era pasca-Soeharto.
| Tokoh Elite Batak | Latar Belakang Utama | Peran dalam Struktur Kekuasaan | Afiliasi Bisnis/Sosial Utama |
| Luhut Binsar Pandjaitan | Militer (Kopassus), Diplomat | Menko Marves, Menko Polhukam, Dubes Singapura 9 | Toba Sejahtra Group (Energi, Tambang, Sawit) 14 |
| T.B. Silalahi | Militer (Letjen) | Menteri PAN, Penasihat Presiden 10 | T.B. Silalahi Center, Yayasan Soposurung 10 |
| Cosmas Batubara | Aktivis (Eksponen ’66) | Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Tenaga Kerja 15 | Industri Properti, Bubur Kertas (Komisaris) 15 |
| Feisal Tanjung | Militer (Jenderal) | Panglima ABRI, Menko Polkam 10 | Struktur Politik Orde Baru 10 |
Luhut Pandjaitan, misalnya, mengelola jaringan loyalitas alumni TNI. Ia melakukan ini untuk memastikan keberlangsungan pengaruh politiknya. Pengaruh ini kemudian digunakan untuk mengamankan aset strategis melalui Toba Sejahtra Group.
Dalam pandangan sosiologi politik, ini merupakan bentuk “kapitalisme politik”. Akses terhadap kekuasaan negara digunakan untuk membangun imperium bisnis pribadi.
Pertumbuhan kekayaan pribadi yang melonjak drastis. Contohnya adalah kenaikan kekayaan Luhut dari Rp7,1 miliar pada 2001 menjadi Rp660 miliar pada 2015. Hal ini menunjukkan betapa efektifnya fusi antara otoritas politik dan akumulasi ekonomi dalam sistem ini.
Dialektika 3H dan Pergeseran Nilai di Perantauan
Akar dari ambisi elite Batak sering kali dikaitkan dengan falsafah 3H. Falsafah ini meliputi Hamoraon (kekayaan), Hagabeon (panjang umur dan banyak keturunan), serta Hasangapon (kehormatan dan status).
Secara tradisional, nilai-nilai ini adalah motivasi untuk bekerja keras dan menuntut ilmu demi menaikkan martabat keluarga.
Namun, di bawah tekanan sistem oligarki, interpretasi terhadap 3H mengalami pergeseran makna yang materialistik dan individualistik.
Hamoraon sebagai Akumulasi Kapital Ekstraktif
Dalam konteks perantauan, Hamoraon tidak lagi dimaknai sebagai kemakmuran bersama di kampung halaman melalui pengolahan sawah dan ladang.
Sebaliknya, kesuksesan diukur dari akumulasi modal finansial di Jakarta. Ini sering kali didapat melalui eksploitasi sumber daya alam di daerah lain. Eksploitasi tersebut bahkan terjadi di Sumatera Utara sendiri.
Semangat mangaranto (merantau) yang didasari keinginan mengubah nasib membuat banyak orang Batak meninggalkan huta. Mereka memiliki tujuan menjadi kaya secara material. Jika berhasil, sering kali lebih banyak diinvestasikan di kota-kota besar daripada di Bona Pasogit.
Hagabeon dan Dinasti Politik Lokal
Nilai Hagabeon, yang menekankan pentingnya keturunan sebagai penerus marga, dalam dunia politik modern bertransformasi menjadi “politik dinasti”.
Keinginan untuk memastikan kekuasaan tetap berada dalam lingkaran keluarga besar. Atau marga tertentu menyebabkan munculnya fenomena Tribalism Dynasties di tingkat kabupaten.
Di Samosir dan Tapanuli Utara, pemilihan kepala daerah sering kali menjadi ajang rivalitas antar-marga besar. Mereka berusaha mengamankan akses terhadap sumber daya negara. Ini dilakukan demi keuntungan kelompoknya sendiri.
Hal ini menghambat meritokrasi. Ini menutup ruang bagi munculnya pemimpin inovatif. Pemimpin tersebut mungkin tidak memiliki dukungan marga yang dominan namun memiliki visi pembangunan yang lebih baik.
Hasangapon dan Pembangunan Seremonial
Hasangapon atau kehormatan sering kali dikejar melalui simbol-simbol luar. Elite Batak yang sukses di Jakarta cenderung mencari legitimasi di kampung halaman. Mereka melakukannya dengan membangun tugu marga yang megah. Mereka juga membangun gereja yang besar atau rumah mewah yang jarang ditempati.18
Kritik intelektual menyebut fenomena ini sebagai “membangun huta secara seremonial,” di mana kontribusi elite lebih bersifat kosmetik daripada struktural.18
Pembangunan tugu yang menghabiskan miliaran rupiah sering kali berdiri tegak di tengah masyarakat. Masyarakat ini masih kesulitan mengakses air bersih atau jalan aspal yang layak. Hal ini menciptakan kontras yang tajam antara kebanggaan marga dan realitas kemiskinan.
Logika Ekstraktif dan Penghancuran Sumber Penghidupan Lokal
Salah satu alasan paling fundamental mengapa elite Batak kurang berkontribusi pada kemakmuran daerahnya adalah keterlibatan mereka dalam logika ekonomi ekstraktif. Logika ini memandang alam Sumatera Utara sebagai aset yang harus dieksploitasi secepat mungkin untuk keuntungan maksimal. Hal itu dilakukan tanpa mempertimbangkan biaya reproduksi ekologis. Mereka juga mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
Konflik Toba Pulp Lestari (TPL) dan Masyarakat Adat
Kasus PT Toba Pulp Lestari (TPL) menunjukkan secara jelas bagaimana kepentingan korporasi besar bisa berbenturan dengan kepentingan masyarakat. Korporasi ini didukung oleh elite di pusat yang berseberangan langsung dengan masyarakat di bawah. Sejak tahun 1980-an, perusahaan ini telah berkonflik dengan berbagai komunitas masyarakat adat di Tano Batak, mulai dari Natumingka hingga Sihaporas.
- Perampasan Ruang Hidup: Ribuan hektare hutan kemenyan merupakan sumber ekonomi utama masyarakat adat selama ratusan tahun. Hutan tersebut telah dikonversi menjadi perkebunan eukaliptus. Tanaman kemenyan bagi orang Batak bukan hanya komoditas ekonomi, melainkan simbol identitas budaya yang kini terancam punah.20
- Kriminalisasi dan Kekerasan: Warga yang berupaya mempertahankan tanah adatnya sering kali menghadapi intimidasi dan kekerasan fisik. Pada Juli 2024, polisi menangkap warga di Lamtoras karena dituduh melakukan kekerasan saat mencoba menghalangi aktivitas perusahaan di hutan mereka. Kejadian serupa berulang pada September 2025 di Sihaporas. Di mana petugas keamanan perusahaan dilaporkan melakukan serangan brutal menggunakan kayu rotan dan pentungan terhadap warga, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.
- Dampak Ekologis Jangka Panjang: Ekspansi industri ekstraktif ini telah menyebabkan deforestasi masif. Data menunjukkan bahwa Sumatera Utara kehilangan sekitar 390 ribu hektare hutan antara tahun 2022-2024.3 Akibatnya, wilayah tersebut menjadi sangat rentan terhadap bencana. Banjir bandang dan longsor terjadi pada November 2025. Bencana ini menelan ratusan korban jiwa. Hal ini merupakan konsekuensi langsung dari rusaknya daerah aliran sungai di hulu Batang Toru. Kerusakan ini disebabkan oleh investasi ekstraktif yang tidak terkendali.3
Elite Batak yang duduk di dewan komisaris memiliki pengaruh politik di pusat. Mereka sering kali bertindak sebagai “perisai” bagi perusahaan-perusahaan ini. Mereka berdalih menjaga iklim investasi.
Mereka cenderung mengabaikan suara masyarakat adat yang mengeluhkan hilangnya harga diri dan sumber pangan karena tanah mereka dirampas.
Inilah yang disebut sebagai “Perjanjian Faustian”: menggadaikan masa depan ekologis daerah asal. Ini dilakukan demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Keuntungan ini hanya dinikmati oleh segelintir orang di puncak kekuasaan.
Patronase Politik dan Efisiensi Pembangunan di Daerah
Sistem patronase yang diwariskan Orde Baru terus berlanjut di era Reformasi melalui mekanisme yang lebih terfragmentasi. Edward Aspinall mendefinisikan Indonesia sebagai “demokrasi patronase.” Dalam sistem ini, kemenangan dalam pemilihan umum sangat bergantung pada pembagian uang, barang, atau kontrak kepada jaringan pendukung. Dalam konteks Tano Batak, sistem ini bekerja melalui perantara atau broker. Broker ini sering kali adalah kepala desa atau tokoh masyarakat. Mereka memiliki akses terhadap sumber daya negara.
Dominasi Birokrat dan Mantan Pejabat dalam Pilkada
Fenomena dominasi mantan birokrat dan pejabat dalam kontestasi politik lokal di Sumatera Utara merupakan indikasi kuat. Akses terhadap struktur negara adalah modal utama untuk berkuasa.
Mereka menggunakan pengetahuan mereka tentang anggaran negara (pork barrel) dan akses ke proyek infrastruktur sebagai alat untuk membeli loyalitas pemilih.
Hal ini menciptakan sistem politik yang mahal. Calon pemimpin harus mengeluarkan biaya besar untuk membiayai tim sukses dan membeli suara. Biaya tersebut akhirnya akan dibayar kembali melalui praktik korupsi setelah mereka menjabat.
| Indikator Politik Lokal | Karakteristik di Kawasan Tano Batak | Dampak terhadap Pembangunan |
| Model Rekrutmen | Berbasis koneksi marga dan loyalitas pada patron partai di pusat.8 | Penempatan pejabat daerah tidak berdasarkan meritokrasi, melainkan balas budi politik.6 |
| Strategi Pemenangan | Vote buying dan distribusi barang melalui jaringan broker informal.6 | Anggaran daerah tersedot untuk proyek-proyek yang menguntungkan tim sukses daripada publik.19 |
| Gaya Kepemimpinan | Cenderung parokial dan memprioritaskan kepentingan kelompok marga tertentu.17 | Terjadi segregasi sosial dan ketidakadilan dalam distribusi program pembangunan antar-kecamatan.17 |
Karena politik lokal sangat bergantung pada patronase, fokus pembangunan sering kali tidak diarahkan pada kebutuhan mendasar masyarakat. Sebaliknya, fokus diarahkan pada proyek-proyek fisik yang mudah dimanipulasi anggarannya. Contohnya, pembangunan jalan yang cepat rusak atau gedung-gedung pemerintahan yang tidak fungsional. Sektor konstruksi menjadi ladang subur bagi praktik kolusi. Kontrak sering kali diberikan kepada perusahaan milik kroni atau anggota keluarga elite politik.
Paradoks Statistik: IPM Tinggi di Tengah Kerentanan Sosial
Jika kita melihat data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kabupaten-kabupaten di kawasan Tano Batak menunjukkan angka yang cukup impresif. Angka tersebut mengesankan jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Namun, angka-angka ini sering kali menyembunyikan realitas kerentanan yang mendalam di tingkat akar rumput.
| Kabupaten | IPM 2021 | IPM 2022 | IPM 2023 | IPM 2024 | Status (2024) |
| Tapanuli Utara | 73,76 | 74,14 | 74,65 | 77,48 | Tinggi 29 |
| Toba | 74,22 | 75,96 | 76,38 | – | Tinggi 30 |
| Humbang Hasundutan | 73,82 | 74,07 | 74,27 | – | Tinggi 31 |
| Samosir | 70,31 | 70,91 | 71,52 | – | Tinggi 30 |
Peningkatan IPM yang rata-rata mencapai 0,47% per tahun di Tapanuli Utara menunjukkan adanya kemajuan dalam hal akses pendidikan. Ini juga menunjukkan kemajuan dalam layanan kesehatan dasar.
Namun, kemajuan ini lebih banyak digerakkan oleh alokasi dana dari pemerintah pusat (DAU/DAK) dan program nasional. Ini bukan karena inisiatif transformatif dari elite lokal yang kembali ke daerah.
Selain itu, IPM tidak mencerminkan ketimpangan penguasaan lahan dan kerusakan lingkungan. Seseorang bisa saja memiliki tingkat pendidikan yang tinggi (meningkatkan IPM). Namun, jika tanah ulayatnya dirampas oleh perusahaan ekstraktif, keberlangsungan hidupnya tetap berada dalam ancaman.
Ketimpangan risiko ekologis menjadi faktor kunci yang diabaikan dalam statistik pembangunan. Keuntungan dari hilirisasi industri atau proyek strategis nasional sering kali menguap. Proyek seperti pariwisata super prioritas Danau Toba lebih sering menguntungkan investor besar dan elite di Jakarta. Masyarakat lokal harus berhadapan dengan polusi. Mereka juga menghadapi kenaikan harga tanah yang tidak terjangkau dan degradasi budaya.2
Mengapa Kontribusi Elite Terhambat? Sebuah Sintesis
Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang tersedia, terdapat beberapa alasan fundamental mengapa elite Batak cenderung terjebak dalam sistem yang tidak produktif bagi kemakmuran daerah asalnya:
1. Ketergantungan pada Struktur Patronase Pusat
Elite Batak yang menduduki jabatan tinggi di Jakarta sering kali harus “berhutang budi” pada sistem yang membesarkan mereka. Dalam sistem demokrasi patronase Indonesia, mempertahankan posisi kekuasaan memerlukan sumber daya yang sangat besar. Sumber daya ini sering kali didapat dari kemitraan dengan modal besar yang bersifat ekstraktif.
Hal ini menciptakan konflik kepentingan. Seorang menteri atau perwira tinggi berdarah Batak sulit membela hak tanah adat di Toba. Kesulitan muncul jika hal tersebut mengganggu kepentingan bisnis korporasi yang merupakan sekutu politiknya di tingkat nasional.
2. Brain Drain dan Orientasi Urban
Tradisi merantau telah menyebabkan pengaliran keluar sumber daya manusia terbaik dari Bona Pasogit ke kota-kota besar.
Anak-anak muda Batak yang berpendidikan tinggi cenderung melihat kesuksesan sebagai kemampuan untuk hidup mapan di Jakarta atau Medan. Mereka tidak berpikir untuk kembali dan membangun desa. Sarana dan prasarana desa masih tertinggal.
Akibatnya, daerah asal mengalami kekosongan inovasi. Kepemimpinan yang progresif juga hilang. Politik lokal tertinggal di tangan mereka yang lebih mahir memanipulasi sentimen marga. Semua ini terjadi daripada mengelola kebijakan pembangunan.
3. Komodifikasi Nilai Adat Dalihan Na Tolu
Sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu (Hula-hula, Dongan Tubu, Boru) seharusnya menjadi mekanisme kontrol sosial dan harmoni. Namun, kini sering kali dikomodifikasi untuk kepentingan politik praktis.
Nilai-nilai ini digunakan untuk memobilisasi suara pemilih secara buta berdasarkan kesamaan marga, bukan berdasarkan visi pembangunan.
Elite politik menggunakan jubah adat untuk membungkus praktik oligarkis mereka. Kritik terhadap kebijakan mereka sering kali dianggap sebagai serangan terhadap martabat marga atau kelompok tertentu.
4. Dominasi Logika Kapitalisme Politik
Sesuai dengan tesis Vedi Hadiz, oligarki di Indonesia telah berhasil bermutasi dan menguasai institusi demokrasi.
Elite Batak adalah bagian integral dari kelas oligarkis ini. Mereka melihat daerah asal mereka melalui perspektif “kapitalisme politik.” Mereka menggunakan pengaruh negara untuk mendapatkan konsesi lahan. Mereka juga mendapatkan izin tambang atau kontrak konstruksi di Sumatera Utara.
Dalam logika ini, kemakmuran daerah hanyalah efek samping (jika ada). Tujuan utamanya adalah pertahanan kekayaan (wealth defense) dan akumulasi kekuasaan.
Tantangan Masa Depan dan Perlunya Rekonstruksi Peran Elite
Situasi tragis banjir bandang dan longsor di akhir tahun 2025 sangat menyedihkan. Peristiwa ini seharusnya menjadi titik balik bagi elite Batak. Mereka perlu mengevaluasi kembali peran mereka.
Jika logika ekstraktif terus dipertahankan, Bona Pasogit akan terus menghadapi bencana ekologis yang lebih parah. Pada akhirnya, hal ini akan menghancurkan basis budaya dan ruang hidup etnis Batak itu sendiri.
Dibutuhkan pergeseran paradigma dari pembangunan yang bersifat seremonial dan ekstraktif menuju pembangunan yang substansial dan regeneratif. Elite Batak di perantauan perlu melihat kembali filosofi 3H dalam konteks kemuliaan bersama. Hamoraon tidak boleh hanya berarti kekayaan pribadi di Jakarta, tetapi harus bertransformasi menjadi kemandirian ekonomi huta. Hasangapon tidak boleh hanya berarti gelar kehormatan dan tugu megah. Ini harus berarti keberanian untuk berdiri membela hak-hak masyarakat adat yang tertindas.
Rekonstruksi sistem politik lokal juga mendesak untuk dilakukan. Memutus rantai patronase memerlukan penguatan masyarakat sipil di daerah. Hal ini agar mereka mampu menuntut akuntabilitas dari para pemimpin mereka. Tindakan ini melampaui sekat-sekat marga yang sempit.
Tidak ada tekanan dari bawah. Elite terjebak dalam kenyamanan sistem oligarki warisan Orde Baru. Mereka akan terus mereproduksi kekuasaan yang destruktif. Ini meninggalkan Bona Pasogit dengan keindahan Danau Toba yang perlahan memudar. Masyarakatnya tetap terpinggirkan di tanah ulayatnya sendiri.
Pembangunan sejati di Tano Batak hanya akan terwujud apabila elite yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan modal dapat melepaskan diri. Mereka harus bebas dari “perjanjian Faustian”. Mereka harus menghindari hubungan dengan oligarki pusat. Mereka harus mulai menempatkan kelestarian ekosistem serta kedaulatan masyarakat adat sebagai prioritas utama. Inilah ujian sesungguhnya bagi integritas dan komitmen para putra terbaik Batak terhadap tanah leluhur. Mereka selalu membanggakan tanah leluhur dalam setiap seremoni adat, namun sering kali mengabaikannya dalam kebijakan politik yang nyata.





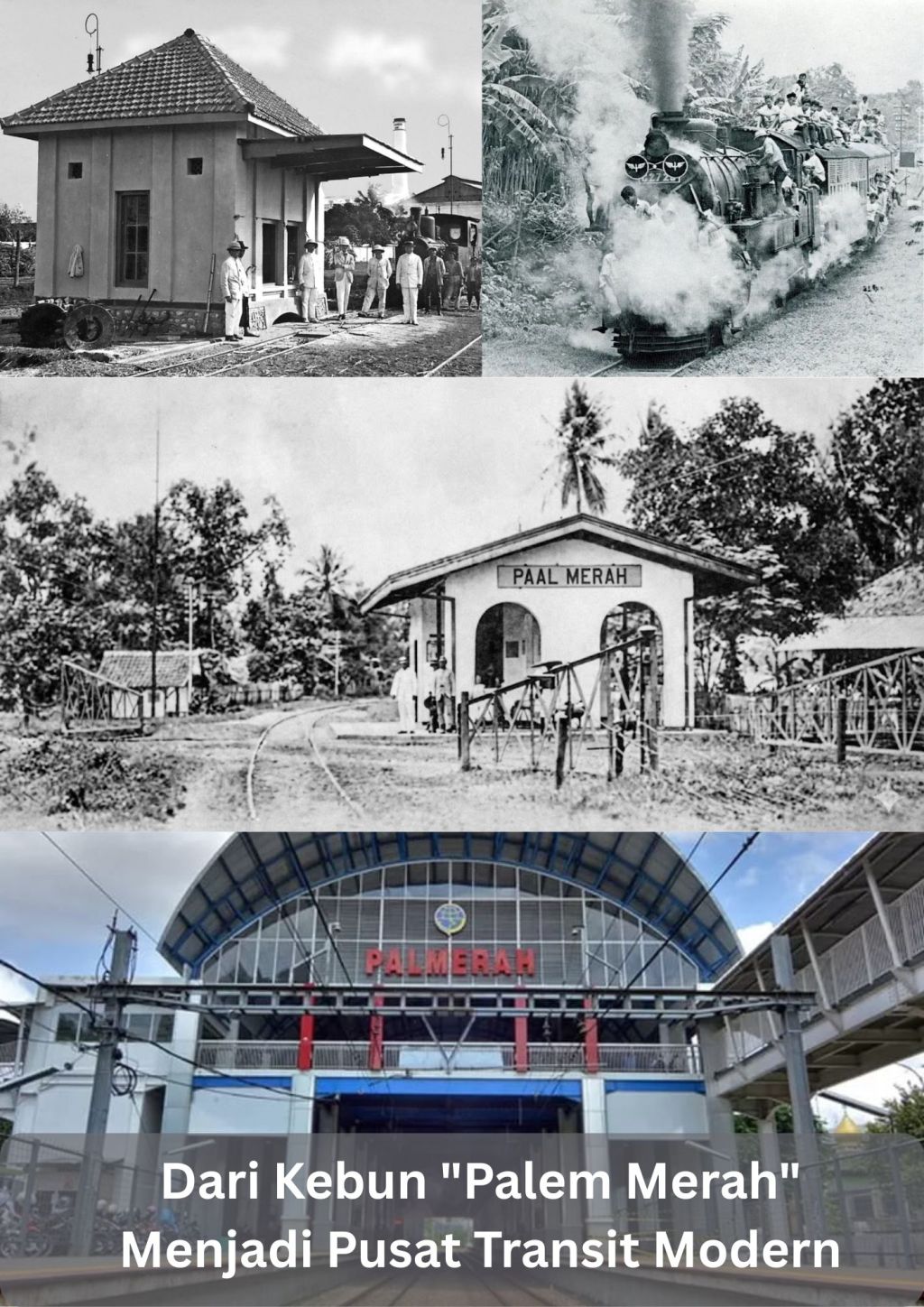
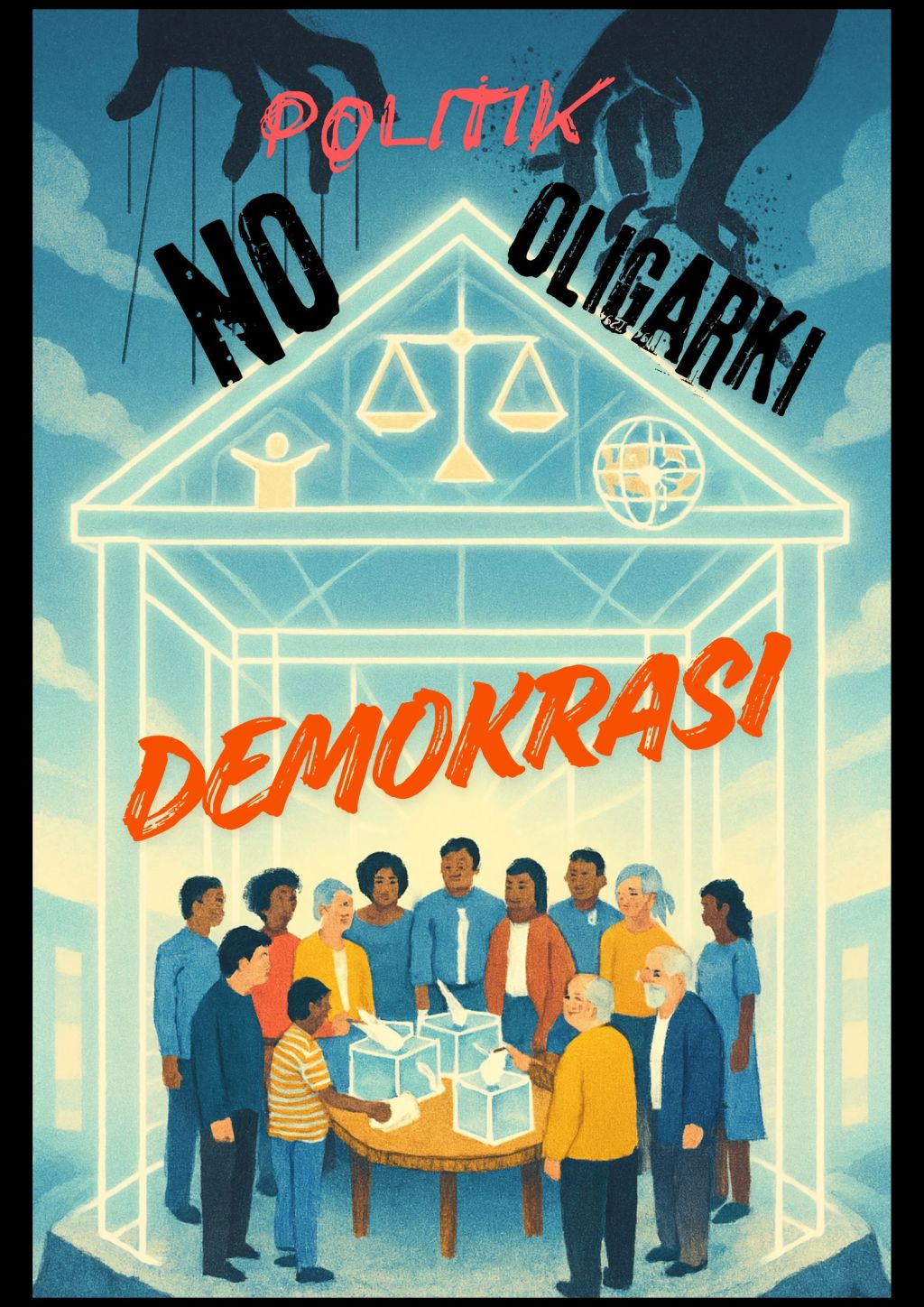



Leave a comment